
BAB 3. Kehilangan Separuh Jiwa
“Setiap waktu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Hargai setiap detiknya sayangi mereka Yang dihadirkan bersamamu.”
**Aku, Rani, si melankolis. Kepribadianku membentukku menjadi seorang introvert, perfeksionis, dan pemikir. Sejak kecil aku terbiasa hidup dalam tuntutan bahwa segala sesuatu harus tampak sempurna—‘no mistake’. Aku belajar menahan air mata, menekan keinginan, menyembunyikan kecewa, hanya agar terlihat kuat di mata orang lain.
Namun, ketika duka mendalam datang, seluruh benteng itu runtuh. Aku mudah terpuruk, menarik diri dari hiruk pikuk dunia, dan butuh waktu lebih lama untuk pulih. Sayangnya, tak banyak yang memahami ini. Bagiku, berdiam diri adalah cara merawat luka, meski di mata orang lain terlihat seperti kelemahan.
Aku harus berjuang sendiri, menggenggam kehilangan yang terlalu berat untuk dipanggul. Kehilangan ini nyata, tak bisa ditolak, dan meski kita semua tahu bahwa kematian adalah pasti, tetap saja tak seorang pun pernah benar-benar siap ditinggal pergi… selamanya.
Dan saat hari itu tiba—hari ketika Ibu pergi tanpa sempat kupeluk untuk terakhir kali—aku menyadari betapa rapuhnya diriku. Di balik segala ketangguhan yang kubangun, ada seorang anak kecil yang sebenarnya hanya ingin bersembunyi di pelukan ibunya. Tapi kini pelukan itu telah tiada, hanya menyisakan sunyi yang panjang, dan aku harus belajar berdiri sendirian di tengah sepi.**
** Ketika Kepergian Mengetuk**
Hari Itu yang Tak Pernah Kulupa
Hari itu, Jumat pagi. Aku masih menerima telepon dari Ibu. Meski berada di ruang ICU COVID-19 dengan alat bantu pernapasan, beliau masih dalam keadaan sadar. Hari itu adalah hari ketiga sejak Ibu ditetapkan dalam status perawatan intensif.
Aku masih bisa mendengar suaranya. Lirih, namun tetap mengalirkan harapan. Aku bertanya, “Ma, lebaran nanti pulang ke rumah kan? Mama, Insya Allah sehat lagi.”
“He-eh,” jawab Ibu sambil mengangguk pelan. Ada jeda, lalu senyum tipis yang seolah ingin menenangkan kami. Bahkan Aisyah ikut bercakap, menyapa oma-nya dengan polos, seolah ingin mengikat janji pertemuan lebaran nanti.
Namun kira-kira jam satu siang, selesai sholat jumat, tiba-tiba rumah sakit menelpon menyampaikan bahwa aku diminta datang karena Ibu kesadarannya menurun. Gegas aku kabari suami dan adikku. Kami langsung ke rumah sakit. Namun hanya satu orang yang boleh menghadap dokter, akhirnya aku yang masuk.
Dokter menjelaskan tentang kondisi Ibu dan kemungkinan terburuk bahwa jika terjadi gagal nafas maka Ibu akan di intubasi.
Satu Minggu Sebelumnya
Ibu mulai mengeluh mual, muntah, dan suhu tubuhnya tinggi. Aku hanya bisa memberikan obat-obatan seadanya di rumah sebagai penanganan sementara. Namun, Ibu meminta untuk dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Dalam pikiranku, ini hanya kambuhnya penyakit asam lambung. Jika dirawat, mungkin akan lebih cepat pulih dari mual dan muntah.
Sesuai prosedur rumah sakit saat itu, semua pasien yang akan dirawat wajib menjalani skrining Covid-19 melalui swab test PCR dan rontgen dada. Karena hasil PCR baru bisa diketahui sekitar tiga hari, Ibu sementara ditempatkan di ruang isolasi khusus pasien suspek Covid-19.
Aku bersikeras menemani Ibu. Awalnya pihak rumah sakit tidak mengizinkan, tetapi dengan alasan ingin menjaga Ibu yang kondisinya lemah, akhirnya mereka memperbolehkan dengan syarat aku menandatangani pernyataan tertulis. Status “suspek Covid” itu tidak aku sampaikan pada Ibu. Aku tidak ingin membuatnya terbebani. Lagi pula, aku yakin ini hanya maag.
Hari pertama, demam Ibu masih tinggi. Obat penurun panas sudah diberikan, namun aku tetap mengompresnya. Ibu merasa kedinginan, lalu kuselimuti sekujur tubuhnya. Hari itu, ia tidak ingin jauh dariku.
“Ran, tidur di sini saja sama Mama,” katanya sambil menarik tanganku dan memelukku.
“Tak apa, Ma. Rani tidur di bawah saja. Kalau kita tidur berdua di ranjang ini, nanti Mama sempit, nggak bisa bergerak,” jawabku sambil memberi alasan.
Akhirnya, Ibu melepaskan tanganku. Memang, tempat tidur di ruang isolasi lebih kecil dibanding ruang VIP tempat Ibu pernah dirawat sebelumnya.
Dua hari berikutnya, kondisi Ibu mulai membaik. Ia sudah mau makan, walaupun sesekali berkata ingin segera pulang. Aku menenangkannya, “Tunggu sembuh betul, baru kita pulang.”
Namun, keesokan harinya hasil PCR keluar. Betapa terkejutnya aku ketika perawat menyampaikan bahwa Ibu positif Covid-19. Malam itu, kami dipindahkan ke ruangan khusus pasien positif. Di dalamnya sudah ada pasien lain yang terlihat lebih baik setelah hampir seminggu dirawat. Meski kaget, aku tetap belum memberitahu Ibu. Aku menunggu waktu yang tepat.
Malam itu, Ibu bisa tidur. Namun, perawat bilang napasnya mulai sesak karena saturasinya turun. Masker oksigen diganti dengan ambubag. Pagi harinya, Ibu masih sempat sarapan. Tiba-tiba ia mengeluh pusing lalu berbaring. Aku segera memanggil perawat. Hasil cek menunjukkan gula darahnya naik, saturasinya semakin turun, dan akhirnya ia harus menggunakan ventilator.
Aku terdiam. Kupikir dengan ventilator, kondisi Ibu akan membaik karena oksigen langsung masuk ke paru-parunya. Namun aku salah. Hari itu, pihak rumah sakit meminta aku pulang. Sebelum pulang, aku juga harus menjalani skrining Covid-19 untuk memastikan apakah aku tertular atau tidak. Status perawatan Ibu resmi naik menjadi ICU Covid, dan tak seorang pun boleh menunggu di sana selain tenaga medis.
Dengan berat hati aku meninggalkan Ibu. Aku memaksakan diri untuk tetap kuat, meyakini bahwa beliau akan sembuh. Malam itu di rumah aku tidak bisa tidur. Dalam sujud panjang sholat malamku, aku memohon kepada Allah agar Ibu diberi kesembuhan, agar kami bisa berkumpul kembali di hari raya.
Doa di Tengah Jarak
Keesokan paginya, suamiku mengantarkan speaker murottal yang biasa menemani Ibu setiap pagi saat di rumah dan sebuah handphone ke rumah sakit, agar Ibu masih bisa menelpon kami. Walau aku tahu, berbicara dengan masker oksigen yang menempel begitu kencang membuatnya sulit bersuara. Aku pun tak tega melihatnya.
Malam harinya, Ibu tetap berusaha menelponku lewat video call. Dengan suara parau, ia menanyakan kabarku, memastikan aku baik-baik saja. Aku tersenyum sekuat tenaga di depannya, meski hatiku sebenarnya perih. Begitu panggilan usai, aku tak kuasa menahan tangis.
Sejak hari itu, air mataku tak pernah berhenti mengalir dalam doa. Setiap kali aku bersujud, hanya satu pintaku: semoga Allah mengangkat sakit Ibu.
Penjelasan dokter membuatku kian terpukul. Adikku sempat memohon agar Ibu diizinkan pulang, agar kami bisa merawatnya sendiri. Kami tahu, Ibu butuh kami di sisinya. Namun, dokter menolak. Status Ibu masih positif, dan hasil swab kedua belum keluar. Jika nanti hasilnya negatif, Ibu baru bisa pindah ke ruang ICU biasa, dan kami berkesempatan menemuinya. Mendengar itu, harapan kecil tumbuh kembali.
Aku pun mencoba lebih dekat dengan Ibu, setidaknya secara jarak. Walau tak bisa masuk ruangannya, aku ingin berada di sekitar rumah sakit. Tapi peraturan saat itu terlalu ketat. Tak ada keluarga pasien yang boleh bermalam, bahkan di selasar rumah sakit sekalipun. Akhirnya, aku memilih menginap di sebuah hotel kecil yang letaknya tak jauh dari sana.
Di kamar hotel yang sunyi, aku hanya menunggu telepon dari rumah sakit—telepon yang semoga membawa kabar baik tentang hasil swab Ibu.
Malam itu aku sempat terlelap, lalu terbangun pukul satu dini hari. Aku berwudhu, mendirikan shalat malam, lalu berulang kali membaca surat Yasin. Dengan air mata yang tak henti jatuh, aku panjatkan doa yang sama: semoga Allah mengangkat sakit Ibu, dan memberiku kesempatan sekali lagi untuk berada di sisinya.
Perpisahan yang Terhalang
Jam tiga pagi, handphoneku berdering. Dengan gemetar aku mengangkatnya, berharap kabar baik, namun suara perawat di seberang memintaku segera datang ke rumah sakit. Dokter sedang melakukan RJP pada Ibuku, dan mereka memintaku berdoa agar beliau selamat.
Dengan tergesa aku berlari keluar kamar hotel sambil mengabarkan pada suamiku. Panik membuat langkahku linglung, aku bahkan sempat bingung mencari pintu keluar di tengah gelapnya dini hari. Allah menghadirkan seorang baik hati yang menuntunku hingga sampai ke rumah sakit.
Aku segera naik ke lantai tempat ibuku dirawat. Di nurse station kulihat seorang dokter muda duduk dengan wajah sendu. Saat aku memperkenalkan diri sebagai keluarga pasien, dia perlahan menyampaikan kabar yang seketika meruntuhkan duniaku. Aku terduduk, kepalaku tertunduk, dan air mataku tak terbendung lagi. Bibirku hanya mampu menyebut nama-Nya.
Dengan hati remuk, aku segera memberi kabar duka kepada suami, adikku, dan pamanku. Aku memohon izin kepada perawat agar bisa melihat jasad Ibu untuk terakhir kalinya, namun ditolak karena harus menggunakan APD lengkap. Hatiku sakit. Ya Allah, izinkan aku menatap wajah ibuku sekali saja sebelum perpisahan ini.
Lalu tiba-tiba seorang perawat memanggilku. Katanya ada perhiasan Ibu yang tidak bisa dilepas, sehingga mereka memintaku membukanya sendiri. Aku tahu, ini jawaban dari doaku. Bergegas aku mengenakan APD dan sarung tangan, sambil diingatkan agar tidak lama dan menahan air mata agar tidak jatuh di tubuh Ibu.
Suara speaker yang memutar murottal menuntunku menemukan kamar itu. Ruangan gelap, hanya terdengar lantunan ayat-ayat suci. Di atas ranjang kulihat ibuku terbaring, seakan sedang tidur. Perlahan kupegang tubuhnya, dari ujung kaki hingga ke kepalanya. Ingin sekali aku memeluknya, tapi aku khawatir air mataku akan membebaninya. Dengan tangan gemetar, aku melepas perhiasan beliau, lalu segera diarahkan keluar oleh perawat untuk menyiapkan segala sesuatu terkait pemakaman.
Aku teringat belum sholat Subuh. Bersama suamiku, aku menuju mushola. Sholat kali ini terasa berbeda—seakan aku hanya ingin berbicara dengan Allah, tapi lidahku kelu. Tak ada kata-kata, hanya air mata yang mengalir sejak takbir hingga salam. Setelah itu, aku menunggu kabar rumah sakit mengenai pemakaman Ibu, di TPU khusus korban Covid-19 yang disediakan pemerintah.
Pemakaman
Ketika jenazah Ibu dibawa dengan kantong jenazah, lalu dimasukkan ke dalam peti dan diangkat menuju ambulan, air mataku tak terbendung. Kami menshalatkannya dengan berhadapan langsung ke arah ambulans. Hanya aku, suami, adikku, dan saudara Ibu yang sempat hadir saat itu, ayah mertuaku yang mengimami sholat jenazah.
Kami mengiringinya ke tempat peristirahatan terakhir. Aku tak diizinkan menyaksikan dari dekat ketika peti diturunkan ke liang lahat. Baru setelah adikku mengumandangkan azan dan tanah mulai ditimbun, aku diperbolehkan mendekat. Andai tidak ingat bahwa Allah melarang meratap di pemakaman, rasanya aku ingin ikut bersama Ibu.
Kesedihan ini kian menyesakkan, bercampur penyesalan: aku tak berada di sisinya saat hembusan napas terakhirnya, aku belum meminta maaf dengan sepenuh hati, aku belum menjadi anak yang berbakti sebagaimana seharusnya. Ya Allah… begitu cepat Engkau memanggil ibuku.
Sepulangnya dari pemakaman, aku kembali ke rumah dengan jiwa kosong, ragaku terasa tanpa nyawa. Aku memilih tidur di kamar Ibu, berharap merasakan kehadirannya. Dalam lelap, aku bermimpi melihat Ibu tertawa bersama anak-anak di sekelilingnya. Mimpi itu sedikit mengobati pedih hatiku, seakan menjadi tanda bahwa beliau kini bahagia di sisi-Mu.
Sejak saat itu, hanya doa yang mampu kupanjatkan di setiap waktu. Aku berusaha melanjutkan amalan yang dahulu beliau cintai: bersedekah kepada anak yatim dan orang-orang tak mampu, terutama di hari Jumat.
Kenangan demi kenangan kembali hadir. Betapa sesungguhnya aku sangat menyayanginya, meski dulu aku sering merasa tertekan oleh aturan-aturannya. Saat kecil hingga remaja, aku jarang merasakan kebahagiaan seperti teman-teman seusiaku. Namun kini aku sadar, itulah caranya mencintai. Pelukan terakhir yang tak sempat ku balas, keinginannya untuk tidur bersamaku yang tak kupenuhi, kini menjadi penyesalan yang membisu di hatiku.
** Kehilangan Tujuan**
S e m u a t a k l a g i s a m a
T e r a s a p a n j a n g h a r i y a n g d i l e w a t i . .
D i k e r a m a i a n t a p i t e t a p s e p i . .
Y a n g k o s o n g i t u b e l u m s e p e n u h n y a t e r i s i . .
k a r e n a t a k m u n g k i n t e r g a n t i . .
T e r u s m e n c o b a m e n g u a t k a n h a t i
M e n c a r i A s a y a n g h a m p i r p e r g i . .
_______
Hari demi hari terasa sungguh berbeda. Meski ada suami dan anak-anak di sisiku, sepi tetap saja menguasai ruang batin. Pikiranku hanya terpaku pada satu hal: kehilangan.
Sebagai seorang dengan karakter melankolis, kehilangan orang tua bagai kehilangan separuh jiwa. Luka itu menyeretku ke dalam keterpurukan, membuatku ingin menarik diri dari dunia luar. Butuh waktu lebih lama untuk pulih, dan itulah yang kini kualami.
Kehilangan Ibu bukan sekadar kehilangan sosok yang kusayangi, melainkan juga kehilangan peta hidup. Aku merasa kosong; seakan semua arti runtuh bersamaan dengan kepergiannya.
ku lebih senang sendiri. Tubuhku seperti kehilangan tenaga, bahkan untuk sekedar makan pun terasa berat. Namun Alhamdulillah, masih ada cahaya kecil dalam pikiranku yang berbisik: aku harus tetap berdiri, aku harus sehat—bukan demi siapapun, tapi demi diriku sendiri.
Di hadapan orang-orang, aku sering tampil seolah baik-baik saja. Seperti memakai topeng: tersenyum di luar, tapi menangis di dalam. Tak seorang pun benar-benar memahami apa yang kurasa, bahkan orang-orang terdekatku. Baru kini kusadari, selama ini Ibulah yang paling mengenalku.
Dalam kesendirian, air mata mengalir tanpa diminta, seakan tak pernah habis. Namun aku percaya, Allah menciptakan air mata bukan hanya untuk melemahkan hati, melainkan juga untuk menguatkannya
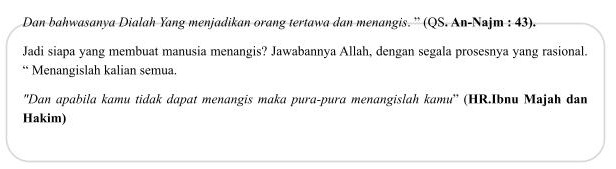
Aku ingin menikmati sedih ini. Satu-satunya penghiburku hanyalah rutinitas setiap minggu: mengunjungi makam Ibu, membawa bunga, membersihkannya dengan tanganku sendiri. Hanya di hadapan pusaranya aku bisa meluruhkan segala rasa, bercerita tentang kesedihan yang tak sanggup kuceritakan pada siapa pun.
Namun hidup harus terus berjalan. Masa berkabung usai, dan aku kembali ke kantor dengan hati yang masih basah oleh air mata. Kata-kata penyemangat dari orang-orang hanya terdengar seperti nyanyian singgah di telinga—tak pernah benar-benar meresap ke dalam hati.
Pernah terlintas keinginan untuk berhenti bekerja. Sejujurnya, alasan terbesar aku bekerja adalah untuk membahagiakan Ibu, membalas sedikit dari jerih payahnya. Baru beberapa hal yang bisa kulakukan: mengajaknya berjalan-jalan ke tempat yang belum pernah dikunjunginya, menemaninya menapaki tanah baitullah. Dan itu pun terasa tak sebanding dengan segala yang telah ia lakukan untukku. Rasanya, apa pun yang kuberikan tak akan pernah cukup.
Ketika niat berhenti itu sampai ke telinga atasanku, beliau menatapku lembut dan berkata, “Membahagiakan ibumu tidak berhenti hanya karena ia telah tiada. Engkau tetap bisa membuatnya bangga, dengan prestasi dan karya yang kau tinggalkan.”
Aku terdiam. Kata-kata itu melekat di benak. Dan aku mulai berpikir, mungkin benar—bekerja dengan sungguh-sungguh adalah salah satu cara untuk tetap menghadiahkan kebanggaan bagi Ibu. Demi Ibu, aku mencoba bertahan.
Kreator : Puspa Raito
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak lahir begitu saja. Di balik perumusan lima sila yang menjadi pondasi bangsa ini, ada pemikiran mendalam dari para tokoh pendiri bangsa, salah satunya adalah Soekarno. Pemikiran Soekarno dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Lalu, apa saja pemikiran Soekarno tentang dasar negara […]
Dalam dunia pendidikan modern, pendekatan sosial emosional semakin banyak dibahas. Salah satu model yang mendapatkan perhatian khusus adalah **EMC2 sosial emosional**. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Definisi EMC2 sosial emosional? Mengapa pendekatan ini penting dalam pembelajaran? Mari kita bahas lebih lanjut untuk memahami bagaimana EMC2 berperan dalam perkembangan siswa secara keseluruhan. Definisi EMC2 Sosial […]
Part 15: Warung Kopi Klotok Sesampainya di tempat tujuan, Rama mencari tempat ternyaman untuk parkir. Bude langsung mengajak Rani dan Rama segera masuk ke warung Kopi Klotok. Rama sudah reservasi tempat terlebih dahulu karena tempat ini selalu banyak pengunjung dan saling berebut tempat yang ternyaman dan posisi view yang pas bagi pengunjung. Bude langsung memesan […]
Part 16 : Alun – Alun Kidul Keesokan paginya seperti biasa Bude sudah bangun dan melaksanakan ibadah sholat subuh. Begitupun dengan Rani yang juga melaksanakan sholat subuh. Rani langsung ke dapur setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Tidak lama disusul oleh Bude dan langsung mengambil bahan masakan serta mengiris bahan untuk memasak. Rani dan Bude sangat […]
Rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Soepomo memiliki peran sangat penting dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, Mr. Soepomo menjelaskan gagasan ini dengan jelas, menekankan pentingnya persatuan dan keadilan sosial. Dengan demikian, fokusnya pada teori negara integralistik membantu menyatukan pemerintah dan rakyat dalam satu kesatuan. Lebih lanjut, gagasan ini tidak hanya membentuk […]
Buy Pin Up Calendar E-book On-line At Low Prices In India After the installation is complete, you’ll have the flexibility […]
Karya Nurlaili Alumni KMO Alineaku Hampir 10 bulan, Pandemi Covid -19 telah melanda dunia dengan cepat dan secara tiba-tiba. Hal […]
Karya Lailatul Muniroh, S.Pd Alumni KMO Alineaku Rania akhirnya menikah juga kamu,,, begitu kata teman2nya menggoda, Yaa,,,Rania bukan anak.yang cantik […]
Karya Marsella. Mangangantung Alumni KMO Alineaku Banyak anak perempuan mengatakan bahwa sosok pria yang menjadi cinta pertama mereka adalah Ayah. […]
Karya Any Mewa Alumni KMO Alineaku Bukankah sepasang sejoli memutuskan bersatu dalam ikatan pernikahan demi menciptakan damai bersama? Tetapi bagaimana […]

Comment Closed: Luka Dalam Cinta Bab 3
Sorry, comment are closed for this post.