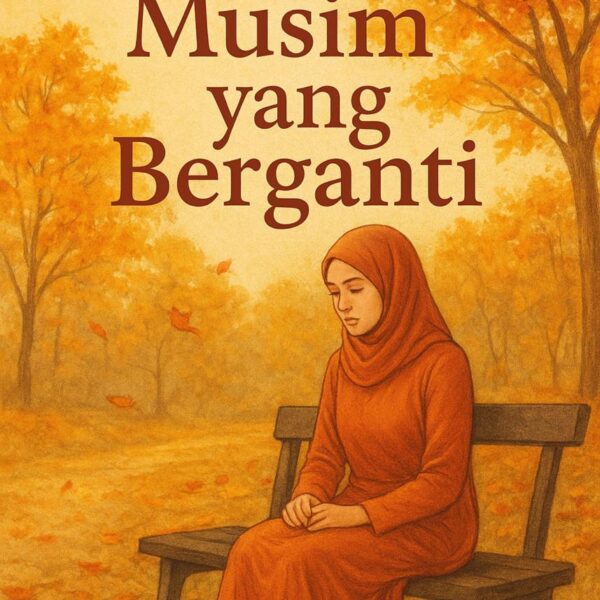
Langkahku terasa asing ketika menyusuri trotoar kota ini. Jalanan yang dulu sederhana kini penuh dengan gedung kaca, lampu-lampu modern, dan papan reklame yang menjulang. Namun, meski wajah kota telah berubah, ada aroma yang tetap sama, aroma hujan yang menempel di aspal, aroma nostalgia yang menempel di hati.
Aku datang ke sini bukan untuk mengenang, tapi untuk bekerja. Setidaknya itu yang aku yakinkan pada diriku sendiri. Tapi siapa yang bisa mengendalikan hati ketika ia dibawa kembali ke tempat di mana semuanya pernah bermula?
Kota ini bukan hanya tentang bangunan, melainkan tentang bayangan. Bayanganmu.
Aku masih bisa mengingat dengan jelas hari itu. Ospek mahasiswa baru, hari penuh teriakan panitia, keringat, dan wajah-wajah tegang. Aku berkeliling membawa buku kecil, mencari tanda tangan senior. Tanganku gemetar, wajahku basah oleh terik matahari.
Dan disanalah kamu. Berdiri santai di dekat gerbang fakultas, wajahmu cerah, matamu jenaka.
Aku memberanikan diri. “Kak… boleh minta tanda tangan?” suaraku lirih, nyaris hilang ditelan riuh.
Kamu menatapku, lalu tertawa kecil. “Tanda tangan aja? Atau sekalian selfie, biar nanti kalau sudah tua bisa pamer ke cucu, ‘lihat, nenek kenal sama senior paling keren di kampus’?”
Aku menatapmu kaget, lalu tersenyum malu. “Ya ampun, pede banget, Kak.”
“Kamu ketawa juga, kan?” balasmu ringan.
Itulah pertama kalinya aku merasa dunia ini lebih ringan. Tawa yang sederhana, tapi mampu memecahkan kebekuan di dadaku. Saat itu aku belum tahu, sebuah rasa diam-diam mulai tumbuh. Rasa yang tidak terencana, tidak disengaja, tapi nyata.
Waktu berjalan, dan entah bagaimana kita makin sering bertemu. Di kantin kampus, di perpustakaan, di taman dekat gedung fakultas.
Suatu sore, kita duduk berdua di bangku kayu. Matahari menurunkan sinarnya, meninggalkan warna oranye di langit. Kamu menggenggam sebotol minuman dingin dan berkata, “Aku ingin kerja di luar kota setelah lulus. Aku nggak mau hidup biasa-biasa aja. Dunia terlalu luas buat cuma dilihat dari sini.”
Aku menoleh padamu, mencoba menyerap semangat itu.
Saat itu, aku percaya kita bisa mengejar mimpi bersama. Tapi ternyata mimpi itu justru menjauhkan kita.
Bertahun-tahun setelahnya, aku sibuk dengan pekerjaanku di Jakarta. Begitu juga kamu, dengan perjalananmu sendiri. Kita jarang berhubungan, tapi bayanganmu selalu terselip di sela-sela waktu.
Hingga suatu malam, telepon itu datang. Suaramu di seberang terdengar berat.
“Aku dijodohkan,” katamu pelan. “Aku nggak bisa menolak. Aku nggak mau mengecewakan orang tua.”
Aku terdiam lama, air mata menetes, lalu hanya bisa berbisik, “Kalau itu pilihanmu, semoga bahagia.”
Padahal hatiku seperti pecah, retakannya menjalar tanpa bisa aku perbaiki. Aku ingin berteriak, ingin bertanya kenapa kita tidak bisa melawan. Tapi aku tahu, jawabannya tak akan mengubah apa pun.
Dan sejak malam itu, kita menjadi dua garis yang berjalan di jalan berbeda, tanpa pernah lagi berpotongan.
Kini aku berdiri lagi di depan gerbang kampus. Gerbang ini masih sama. Tapi bagiku, ia terasa seperti pintu waktu membawaku kembali pada hari-hari yang penuh tawa, pada percakapan yang tak pernah selesai, pada cinta yang tak pernah sempat dirayakan.
Aku menutup mata. Dalam bayanganku, aku masih melihatmu berjalan cepat sambil melambaikan tangan. Masih mendengar tawamu memecah hujan sore. Masih merasakan tatapanmu yang membuat dunia terasa lebih sederhana.
Tapi saat aku membuka mata, hanya ada kesunyian. Kamu kini entah di mana, bersama keluargamu. Dan aku berdiri sendiri, ditemani kenangan yang tak lagi bisa kusentuh.
Cinta yang pernah ada di antara kita kini seperti bunga kering yang terselip di buku lama. Warnanya pudar, rapuh disentuh, tapi aromanya masih samar tertinggal. Ia tak lagi hidup, tapi ia pernah ada dan itu cukup untuk membuatku tersenyum saat menemukannya kembali.
Aku sadar, aku tidak lagi mencintaimu dengan keinginan untuk memiliki. Aku mencintaimu seperti mencintai lagu lama: tidak lagi diputar setiap hari, tapi ketika terdengar, masih membuat hati hangat.
Aku belajar sesuatu dari semua ini: tidak semua cinta harus bertahan untuk menjadi berarti. Ada cinta yang hadir sebentar, hanya untuk mengajarkan kita arti getaran pertama, arti kehilangan, dan arti merelakan.
Cinta sejati bukan selalu soal menggenggam erat. Kadang, cinta sejati justru ada dalam melepas dengan doa yang tulus.
Dan di kota lama ini, aku akhirnya mengerti: ada cinta yang ditakdirkan untuk dikenang, bukan untuk dimiliki.
Langkahku meninggalkan gerbang kampus dengan berat, seolah ada sesuatu yang menarikku untuk tetap tinggal di sana. Tetapi hidup tak pernah mengizinkan kita berlama-lama di persimpangan. Aku harus kembali ke kenyataan: sebuah rapat penting menantiku besok pagi.
Namun, sepanjang perjalanan menuju hotel, pikiranku masih terikat pada satu hal: bayanganmu. Anehnya, meski aku sudah berusaha keras menutup buku itu bertahun-tahun lalu, kota ini seperti membukanya kembali, halaman demi halaman.
Malam turun perlahan. Dari jendela kamar hotel, aku memandang lampu kota yang berkelap-kelip. Seharusnya aku sibuk menyiapkan presentasi, tapi entah kenapa, pikiranku melayang ke masa lalu.
Kupandangi meja kecil di dekat ranjang, kosong kecuali sebuah buku catatan yang kubawa. Dengan ragu, aku menuliskan sesuatu:
“Mengapa bayanganmu masih tinggal di sini, padahal aku sudah belajar melepas? Apakah ini cinta, atau sekadar luka yang tak pernah sembuh?”
Tanganku terhenti. Ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Aku sadar, aku tidak lagi mencintaimu seperti dulu. Tapi aku juga tahu, aku belum sepenuhnya berdamai dengan kehilangan itu.
Keesokan paginya, aku menuju ruang rapat. Di sana aku bertemu dengan banyak orang penting, kolega dari berbagai kota. Salah satunya seorang pria muda bernama Adrian. Ia sopan, penuh ide segar, dan memiliki tawa yang mengingatkanku… padamu.
Kami berdiskusi panjang tentang proyek, lalu tanpa sadar percakapan bergeser ke hal-hal pribadi.
“Aku suka kota ini,” kata Adrian sambil menyesap kopi. “Terlalu banyak kenangan, meski beberapa di antaranya pahit.”
Aku menatapnya sejenak. “Kenangan pahit pun kadang tetap kita jaga, ya?”
Adrian tersenyum samar. “Karena dari situlah kita belajar. Kalau tidak ada pahit, mungkin kita takkan pernah tahu arti manis.”
Perkataannya menusuk sesuatu dalam diriku. Aku terdiam, lalu hanya mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada orang yang mengerti bahasa sunyiku.
Malam itu, aku menatap cermin di kamar hotel. Wajahku yang lelah menatap balik dengan mata sendu. “Kapan aku akan benar-benar bebas darimu?” bisikku lirih.
Kenangan itu seperti hantu, tidak lagi nyata, tapi tetap hadir. Aku tahu aku harus berdamai, tapi bagian dari diriku masih ingin menggenggam.
Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi, aku berada di sebuah stasiun kereta. Kereta panjang berhenti di depanku, pintunya terbuka. Di dalam, kulihat dirimu berdiri, melambaikan tangan.
“Ayo naik,” katamu.
Tapi setiap kali aku melangkah, pintu itu menutup kembali. Kereta bergerak perlahan, meninggalkanku di peron. Aku berlari mengejar, tapi tidak pernah berhasil.
Aku terbangun dengan napas terengah. Baru saat itu aku mengerti: kamu adalah kereta yang sudah lama berangkat, dan aku adalah penumpang yang datang terlambat. Tidak peduli seberapa cepat aku berlari, aku tidak akan pernah bisa menyusulmu.
Aku duduk lama di tepi ranjang, membiarkan makna itu meresap.
Mungkin inilah yang disebut berdamai: bukan melupakan, bukan juga terus berharap, melainkan menerima bahwa ada kereta yang memang bukan untuk kita naiki.
Aku menatap jendela yang perlahan disinari cahaya pagi. Di luar sana, dunia masih berjalan, menawarkan stasiun-stasiun baru, pertemuan-pertemuan baru.
Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku hanya perlu belajar melangkah lebih ringan, bukan lagi mengejar kereta yang sudah pergi, melainkan menyiapkan hati untuk menyambut perjalanan yang menunggu di depan.
Keesokan hari, setelah rapat selesai, aku menyusuri koridor hotel dengan langkah ringan. Perbincangan dengan Adrian masih terngiang. Entah mengapa, ada sisi diriku yang merasa sedikit lega seakan ada orang asing yang diam-diam memahami luka yang tidak pernah kuceritakan.
Namun, rasa itu belum sempat ku selami lebih jauh ketika sebuah kabar mengejutkan datang.
Seorang kolega menghampiriku. “Nanti malam ada jamuan kecil dengan beberapa alumni kampus sini. Katanya, beberapa senior juga akan datang. Kamu mau ikut, ngga?”
Aku mengangguk refleks, tanpa berpikir panjang. Tapi kemudian, dadaku mendadak sesak. Alumni kampus. Kota ini. Lalu pikiranku segera melompat pada satu nama: dirimu.
Sepanjang siang, tanganku bergetar setiap kali menulis catatan. Pikiranku berputar: Bagaimana kalau aku benar-benar bertemu dengannya?
Malamnya, aku tiba di restoran. Ruangan dipenuhi cahaya hangat, suara tawa, dan musik pelan yang mengalun. Aku menyalami satu demi satu tamu, hingga mataku berhenti pada sosok yang tak asing.
Kamu.
Kamu berdiri di seberang ruangan, mengenakan kemeja biru. Wajahmu masih sama, meski ada garis lelah yang tidak kukenal dulu.
Dunia mendadak mengecil. Suara-suara di ruangan lenyap, menyisakan hanya detak jantungku yang memekakkan telinga.
Kamu menoleh, tatapan kita bertemu. Hanya sekejap, tapi cukup untuk menyalakan kembali semua yang sudah berusaha kupadamkan.
Tak lama kemudian, kamu menghampiri. “Hai… sudah lama sekali, ya?” Suaramu rendah, sedikit canggung.
Aku tersenyum tipis. “Ya. Bertahun-tahun.”
Ada hening di antara kita. Hening yang berisi ribuan kata yang tak terucap.
Kamu lalu berkata pelan, “Aku dengar kamu sibuk sekarang. Keliling kota, kerjaan bagus. Aku senang dengarnya.”
Aku mengangguk dan malam itu amat kaku. Kamu bercerita dengan mata berbinar bahwa kamu sudah memiliki seorang anak yang lucu.
Sepulang dari jamuan, aku berjalan kaki sendirian di jalanan kota. Lampu jalan berpendar samar, bayangan panjang mengikuti langkahku. Di kepalaku, wajahmu masih jelas. Tapi kali ini berbeda. Tatapannya sudah berbeda dengan tatapan nya dahulu.
Seketika aku teringat pada Adrian. Percakapan kami tentang kenangan pahit. Tawa ringannya yang menenangkan. Ada sesuatu yang mungkin bisa tumbuh di sana, bukan sebagai pengganti, tapi sebagai jalan baru.
Namun, hatiku gamang. Apakah aku siap membuka ruang baru, atau aku masih terlalu terpaku pada bayangan lama?
Aku berhenti di sebuah jembatan kecil, menatap air sungai yang berkilau terkena cahaya lampu. Bayangan lampu di permukaan air bergetar, tidak pernah utuh.
Di sanalah aku sadar: kamu adalah bayangan di air. Indah, tapi rapuh. Sekuat apa pun aku mencoba menggenggam, ia akan pecah dalam genggaman. Sementara cahaya, ia ada di atas sana, nyata, menunggu untuk dilihat. Mungkin Adrian, mungkin orang lain, mungkin bahkan diriku sendiri yang lebih utuh.
Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri: aku tidak akan lagi berjalan dengan pandangan ke belakang. Masa lalu memang selalu indah untuk dikenang, tapi terlalu berat untuk terus dipikul.
Cinta yang pernah ada di kota ini akan selalu menjadi bagian dari diriku, bukan untuk disesali, tapi untuk dihargai.
Dan jika suatu hari aku menemukan cinta baru, aku ingin datang dengan hati yang tidak lagi dipenuhi bayangan, tapi dengan cahaya yang siap menyinari perjalanan berikutnya.
Pagi itu, aku duduk di kafe kecil dekat hotel. Secangkir kopi hitam mengepul di depanku, aromanya menenangkan. Namun, pikiranku masih kusut setelah pertemuan semalam pertemuan yang tak pernah kubayangkan akan terjadi, pertemuan yang seperti membuka luka lama.
Aku menatap ke luar jendela. Orang-orang berlalu-lalang, sibuk dengan hidup mereka sendiri. Dan aku bertanya dalam hati: berapa lama lagi aku akan terus membiarkan masa lalu mengikatku?
Adrian datang terlambat pagi itu, dengan kemeja tergesa tapi tetap menebar senyum. Ia menatapku sejenak, lalu berkata pelan, “Kamu terlihat lelah. Semalam ketemu seseorang?”
Aku terdiam, kaget dengan ketepatan tebakannya. “Kenapa kamu tanya begitu?”
Adrian mengangkat bahu. “Aku pernah ada di posisi itu. Wajah orang yang ketemu cinta lamanya selalu kelihatan campur aduk. Antara bahagia, sedih, dan bingung.”
Aku menunduk, merasa telanjang di depan kata-katanya. “Ya… aku ketemu dia.”
“Dan?”
Aku menghela napas panjang. “Dia sudah bahagia. Sama orang lain. Dan aku… aku masih harus belajar berdamai.”
Adrian tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatapku dengan tenang, seakan memberi ruang bagi hatiku untuk jujur.
Malamnya, aku menulis lagi di buku catatan kecilku. Tulisan tanganku bergetar, tapi kata-kata itu akhirnya keluar:
“Mungkin bukan dia yang tidak bisa kulepaskan. Mungkin sebenarnya aku takut kehilangan bagian dari diriku sendiri, diriku yang dulu, yang pernah merasa begitu hidup bersamanya.”
Aku tersadar: selama ini, aku bukan hanya merindukan dirinya, tapi juga merindukan versi diriku yang lebih ringan, lebih berani bermimpi, lebih penuh tawa.
Dan untuk itu, aku harus belajar menemukan diriku kembali. Bukan lewat dirinya, bukan juga lewat orang baru, tapi lewat langkah-langkah kecil yang kutapaki sendiri.
Aku membayangkan hatiku seperti sebuah kamar tua yang lama tak disentuh. Di dalamnya ada foto-foto lama, surat-surat yang tak pernah terkirim, bunga kering di buku usang. Semua itu indah, tapi berdebu.
Kini, sudah waktunya aku membuka jendela kamar itu, membiarkan cahaya masuk. Aku tidak akan membakar kenangan, karena kenangan bukan musuh. Aku hanya perlu menatanya kembali: menaruhnya di rak yang tepat, agar ia tidak lagi berserakan dan melukai langkahku.
Hari itu, aku tiba lebih awal di bandara. Pekerjaanku di kota lama selesai, dan aku siap kembali ke kehidupanku yang biasa. Namun, kali ini ada rasa berbeda: bukan lagi berat meninggalkan, melainkan ringan, seolah aku baru saja menutup sebuah bab dengan tenang.
Aku duduk di ruang tunggu, membuka laptop. Tapi pandanganku terganggu oleh pesan singkat yang masuk.
“Sudah di bandara? Kita ketemu di kafe depan gate, ya?”
Adrian.
Aku tersenyum samar. Ada kehangatan kecil yang terasa baru, sederhana, tapi nyata.
Adrian sudah duduk ketika aku datang, dengan secangkir teh di tangannya. Ia melambai. “Hei, aku kira kamu bakal langsung kabur tanpa pamit.”
Aku tertawa kecil. “Aku orangnya sopan, kok. Selalu pamit dengan baik.”
Kami berbincang ringan. Tentang proyek kerja, tentang kota lama yang penuh kenangan, hingga tentang hal-hal remeh seperti makanan favorit.
Lalu, Adrian menatapku serius. “Kamu tahu… kamu berbeda sekarang. Waktu pertama kali ketemu, aku lihat matamu kayak bawa beban berat. Tapi hari ini, matamu lebih tenang.”
Aku terdiam. Kata-katanya seperti cermin yang menunjukkan sesuatu yang baru kusadari.
“Ya,” jawabku pelan. “Aku memang sudah belajar melepas. Dan ternyata, rasanya… lega.”
Pesawat belum boarding, jadi aku menatap keluar jendela bandara. Cahaya matahari sore masuk menembus kaca, jatuh ke wajahku. Ada sesuatu yang terasa hangat di dada.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak lagi merasa dikejar bayangan. Tidak ada lagi luka yang mengikat pergelangan kaki. Hanya ada jalan panjang di depan, dengan cahaya yang mengiringi.
Adrian tersenyum sambil berkata, “Kalau kamu mau, mungkin kita bisa saling menemani. Nggak usah buru-buru. Nggak usah pakai janji. Cukup jalan beriringan, lihat apakah kita nyaman.”
Aku menoleh padanya. Ada rasa takut, tapi juga rasa ingin mencoba. Bukan karena aku butuh pengganti, tapi karena aku sudah siap memberi ruang baru.
Aku membayangkan hatiku seperti sebuah jendela tua yang selama ini tertutup rapat, tirainya kusut, debunya tebal. Dan hari ini, aku akhirnya menarik tirai itu. Cahaya masuk pelan, menyinari setiap sudut, membuat kamar itu terasa hidup kembali.
Cahaya itu bukan hanya tentang Adrian. Cahaya itu adalah keberanianku untuk hadir di masa kini, tanpa dihantui masa lalu.
Ketika pesawat lepas landas, aku menatap kota lama yang mengecil di bawah sana. Kota yang dulu menyimpan bayangan cinta yang tidak pernah jadi nyata, kini kupandang dengan rasa syukur.
Aku tidak lagi terikat pada “seandainya”. Kini aku berjalan di jalanku sendiri, dengan hati yang lebih utuh.
Mungkin nanti akan ada cinta baru, mungkin tidak. Tapi aku tahu satu hal: aku sudah siap untuk hidup sepenuhnya, bukan lagi sebagai tawanan kenangan, melainkan sebagai jiwa yang bebas menatap cahaya.
Dan itu… adalah awal dari sebuah perjalanan baru.
Malam ini aku menulis di atas meja kecil di apartemenku. Kota yang berbeda, tapi hati yang kini terasa lebih damai. Di luar jendela, lampu-lampu kota berkelip, seperti bintang yang jatuh ke bumi, mengingatkanku bahwa keindahan selalu hadir di sela-sela kegelapan.
Aku teringat kembali pada hari pertama aku bertemu dengannya di kampus, bertahun-tahun lalu. Senyumnya yang ringan, candaannya yang sederhana, kehadirannya yang pernah membuat dunia terasa penuh warna. Kenangan itu tak lagi menyakitkan. Kini ia menjadi seperti halaman pertama sebuah buku: tetap penting, tapi bukan keseluruhan cerita.
Aku sadar, hidup adalah kumpulan pertemuan dan perpisahan, seperti musim yang datang dan pergi. Ada musim hujan yang membuat kita basah oleh air mata, ada musim panas yang menyinari luka agar kering. Dan ada musim semi, musim baru di mana bunga berani tumbuh setelah tanah lama retak oleh dingin.
Cinta pertama bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenang dengan tenang. Ia adalah benih yang mungkin tidak tumbuh menjadi pohon, tapi tetap memberi jejak pada tanah tempat kita berpijak. Dari sana, kita belajar tentang rindu, kecewa, keberanian, dan akhirnya: tentang melepaskan.
Kini, aku tahu… melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah bentuk tertinggi dari cinta, cinta yang memberi ruang bagi masing-masing untuk bahagia, meski tidak lagi bersama.
Adrian mungkin akan hadir dalam kisah baruku, atau mungkin tidak. Tapi yang terpenting, aku sudah menemukan kembali diriku sendiri. Aku sudah bisa menatap cermin tanpa bayangan di belakangku.
Dan malam ini, sebelum menutup buku harianku, aku menuliskan satu kalimat sederhana:
“Aku tidak lagi takut kehilangan, karena aku telah menemukan diriku sendiri.”
Lalu aku menutup halaman itu, seperti seseorang yang akhirnya berani menutup sebuah bab panjang, bukan dengan air mata, melainkan dengan senyum.
Kreator : Rosita Taher
Part 15: Warung Kopi Klotok Sesampainya di tempat tujuan, Rama mencari tempat ternyaman untuk parkir. Bude langsung mengajak Rani dan Rama segera masuk ke warung Kopi Klotok. Rama sudah reservasi tempat terlebih dahulu karena tempat ini selalu banyak pengunjung dan saling berebut tempat yang ternyaman dan posisi view yang pas bagi pengunjung. Bude langsung memesan […]
Part 16 : Alun – Alun Kidul Keesokan paginya seperti biasa Bude sudah bangun dan melaksanakan ibadah sholat subuh. Begitupun dengan Rani yang juga melaksanakan sholat subuh. Rani langsung ke dapur setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Tidak lama disusul oleh Bude dan langsung mengambil bahan masakan serta mengiris bahan untuk memasak. Rani dan Bude sangat […]
Dalam dunia pendidikan modern, pendekatan sosial emosional semakin banyak dibahas. Salah satu model yang mendapatkan perhatian khusus adalah **EMC2 sosial emosional**. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Definisi EMC2 sosial emosional? Mengapa pendekatan ini penting dalam pembelajaran? Mari kita bahas lebih lanjut untuk memahami bagaimana EMC2 berperan dalam perkembangan siswa secara keseluruhan. Definisi EMC2 Sosial […]
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak lahir begitu saja. Di balik perumusan lima sila yang menjadi pondasi bangsa ini, ada pemikiran mendalam dari para tokoh pendiri bangsa, salah satunya adalah Soekarno. Pemikiran Soekarno dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Lalu, apa saja pemikiran Soekarno tentang dasar negara […]
Part 14: Kopi Klotok Pagi hari yang cerah, secerah hati Rani dan semangat yang tinggi menyambut keseruan hari ini. Ia bersenandung dan tersenyum sambil mengiris bahan untuk membuat nasi goreng. Tante, yang berada di dekat Rani, ikut tersenyum melihat Rani yang bersenandung dengan bahagia. “Rani, kamu ada rasa tidak sama Rama? Awas, ya. Jangan suka […]
Buy Pin Up Calendar E-book On-line At Low Prices In India After the installation is complete, you’ll have the flexibility […]
Karya Nurlaili Alumni KMO Alineaku Hampir 10 bulan, Pandemi Covid -19 telah melanda dunia dengan cepat dan secara tiba-tiba. Hal […]
Karya Lailatul Muniroh, S.Pd Alumni KMO Alineaku Rania akhirnya menikah juga kamu,,, begitu kata teman2nya menggoda, Yaa,,,Rania bukan anak.yang cantik […]
Karya Marsella. Mangangantung Alumni KMO Alineaku Banyak anak perempuan mengatakan bahwa sosok pria yang menjadi cinta pertama mereka adalah Ayah. […]
Karya Any Mewa Alumni KMO Alineaku Bukankah sepasang sejoli memutuskan bersatu dalam ikatan pernikahan demi menciptakan damai bersama? Tetapi bagaimana […]

Comment Closed: Musim Yang Berganti
Sorry, comment are closed for this post.