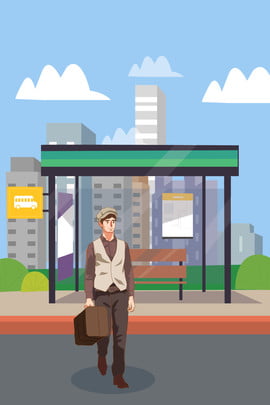
Langit malam menyelimuti kota dengan kelap-kelip neon yang tak pernah padam. Cahaya dari papan iklan raksasa berwarna biru dan merah menciptakan refleksi abstrak di jendela apartemen lantai tiga puluh lima. Dari kejauhan, gemerlap gedung-gedung pencakar langit menyerupai lautan bintang buatan manusia. Namun, di dalam apartemen modern ini, hanya ada kesunyian yang menempel erat di dinding-dinding kaca.
Arga duduk di sofa abu-abu yang terlihat mahal tetapi tidak nyaman. Punggungnya bersandar setengah hati, tangan kirinya memegang secangkir kopi hitam yang mulai dingin. Di depannya, layar laptop menyala dengan cahaya kebiruan, menampilkan grafik-grafik naik turun yang monoton. Di pojok kanan bawah layar, deretan angka menunjukkan saldo rekening yang stabil dan, bagi kebanyakan orang, mengundang iri. Namun, bagi Arga, angka-angka itu tak lebih dari sekadar hiasan digital.
Ia menghela napas panjang. Kepalanya bersandar ke sandaran sofa, memejamkan mata sejenak, tetapi pikirannya tetap bekerja seperti mesin tua yang berderak-derak tanpa henti. Selama bertahun-tahun, ia mengejar yang orang sebut sebagai kesuksesan: gelar akademik, karir di perusahaan multinasional, gaji besar, apartemen mewah, dan mobil impian. Semuanya ada dalam genggamannya. Namun, malam ini, ia merasa kosong.
“Untuk apa semua ini kalau aku bahkan tidak tahu siapa diriku?” gumamnya pelan, suaranya tenggelam di antara dengung AC yang konstan.
Pertanyaan itu seperti benalu yang sudah lama bersarang di kepalanya, tetapi baru malam ini ia benar-benar berani menatapnya langsung. Ia tahu ini bukan pertama kali ia merasa gelisah, tetapi biasanya pekerjaan bisa mengalihkan perhatian. Namun, malam ini berbeda. Seolah ada sesuatu yang mendesaknya untuk berhenti sejenak dan bertanya—apa sebenarnya yang ia cari?
Ia menutup laptop dan meletakkannya di meja kopi di depannya. Tangan kanannya meraih ponsel, lalu membuka media sosial. Foto-foto teman-temannya yang sedang liburan di pantai, mendaki gunung, atau sekadar makan malam romantis dengan pasangan memenuhi beranda. Ia menggeser layar tanpa minat, lalu melempar ponselnya ke sisi sofa. Bahkan media sosial pun tidak mampu memberinya pelarian.
Arga berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap kota. Matanya menatap gedung-gedung tinggi yang berjajar seperti tentara tak bernyawa. Lampu-lampu jalan membentuk garis-garis panjang berwarna oranye yang membelah kota seperti nadi elektronik. Di kejauhan, klakson mobil terdengar samar, namun tidak cukup keras untuk mengganggu keheningan di dalam apartemennya.
“Mungkin aku harus pergi,” bisiknya pada dirinya sendiri. “Meninggalkan semua ini sejenak.”
Ia kembali ke kamar, membuka lemari, dan mengeluarkan ransel hitam yang sudah lama tidak digunakan. Tangannya mengisi ransel itu dengan pakaian secukupnya, beberapa buku catatan, dan kamera yang selalu ia simpan di laci paling bawah. Tidak ada rencana matang, tidak ada tiket pesawat atau reservasi hotel. Ia hanya tahu bahwa ia harus pergi, mencari sesuatu yang selama ini hilang.
Ketika ranselnya sudah penuh, ia duduk di tepi tempat tidur dan menatap dinding putih di depannya. Pikirannya melayang ke masa lalu—ke saat-saat dimana hidup terasa lebih sederhana, ketika ia tidak perlu berpikir terlalu keras tentang tujuan hidup. Ia ingat saat kecil, duduk di teras rumah neneknya, mendengarkan cerita-cerita rakyat sebelum tidur. Ia ingat suara hujan yang jatuh di atas genting dan aroma tanah basah yang menenangkan.
Dimana perasaan itu sekarang? Mengapa hidup yang dulu terasa penuh warna, kini berubah menjadi monokrom?
Kepalanya tertunduk, dan ia merasakan matanya mulai panas. Tetapi sebelum air mata itu jatuh, ia bangkit. Tidak ada waktu untuk tenggelam dalam emosi. Ia harus bergerak.
Di dapur, ia meneguk sisa kopi dingin dari cangkirnya. Rasanya pahit, tetapi ia tidak peduli. Ia mematikan semua lampu di apartemen, meninggalkan hanya satu lampu kecil di dekat pintu. Setelah memastikan semuanya terkunci, ia melangkah keluar. Udara malam menyambutnya dengan hembusan dingin yang menusuk kulit.
Di jalan, ia memesan taksi online dan memberi tahu sopir tujuan terminal bus terdekat. Selama perjalanan, ia hanya diam, memandang keluar jendela. Jalanan kota yang biasanya sibuk kini tampak lebih lengang. Hanya beberapa kendaraan melintas, dan lampu jalan membentuk pola bayangan yang bergerak lambat di aspal.
“Malam-malam begini mau kemana, Mas?” tanya sopir taksi mencoba membuka percakapan.
“Nggak tahu, Pak. Kemana kaki membawa saja.” jawab Arga tanpa menoleh.
Sopir itu tertawa kecil, tetapi tidak bertanya lagi. Mungkin ia sudah terbiasa dengan penumpang yang punya cerita unik di tengah malam.
Setibanya di terminal, Arga turun dan membayar ongkos. Ia berjalan perlahan melewati deretan bus yang berjejer. Udara di sini lebih dingin daripada di kota, dan aroma asap knalpot bercampur dengan bau kopi dari warung kecil di sudut terminal. Ia berhenti sejenak, memandangi papan jadwal keberangkatan.
“Jogja, Bandung, Malang, Bali… ke mana aku harus pergi?” pikirnya.
Pilihan itu membuatnya ragu sejenak, tetapi kemudian matanya menangkap tulisan kecil di pojok papan: Tujuan Pantai Selatan.
“Pantai,” gumamnya.
Ada sesuatu tentang laut yang selalu memanggilnya, seperti rumah kedua yang tak pernah ia kunjungi cukup lama. Tanpa berpikir panjang, ia membeli tiket dan menunggu di bangku terminal.
Selama menunggu, ia mengeluarkan buku catatan kecil dari ranselnya. Di halaman pertama, ia menulis sebuah kalimat pendek:
“Malam ini adalah awal perjalanan untuk menemukan diriku sendiri.”
Bus datang, dan ia naik ke dalam. Kursinya berada di dekat jendela, memberikan pemandangan jalanan malam yang sepi. Begitu bus mulai bergerak, Arga menyandarkan kepalanya ke kaca, membiarkan matanya terpejam. Suara mesin yang menderu menjadi pengantar tidur yang lembut.
Saat bus melaju meninggalkan kota, pikirannya perlahan mereda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa sedikit lebih ringan. Mungkin karena ia tahu bahwa ia akhirnya bergerak, bukan lagi terjebak dalam rutinitas yang membelenggu.
Di luar, lampu jalan satu per satu menghilang, digantikan oleh kegelapan desa-desa kecil yang hanya diterangi cahaya bintang. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di ujung perjalanan ini, tetapi untuk saat ini, ia tidak peduli.
Malam itu, di dalam bus yang bergetar pelan, Arga tertidur dengan tenang. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya melewati pantai, gunung, dan jurang emosional yang dalam. Tetapi yang ia tahu, ia siap menghadapinya—apa pun yang terjadi.
Dan di balik semua itu, ada suara kecil di dalam hatinya yang terus berbisik: Aku akan menemukan jalanku pulang.
Langit jingga senja menyelimuti garis pantai yang sepi, hanya ditemani desiran angin dan deburan ombak yang menyentuh pasir putih. Di tepi pantai itu, seorang pria dengan tubuh tinggi dan rambut acak berlutut di atas pasir, tangannya membentuk gestur meditasi sederhana. Arga memejamkan mata, mencoba menarik napas panjang seakan berharap udara laut bisa menyedot segala beban yang bersarang di dadanya.
“Hirup… hembuskan… lepaskan…” gumamnya pelan, seperti mantra yang diulang-ulang tanpa keyakinan penuh.
Ombak menggulung lembut, membawa irama alami yang, bagi kebanyakan orang, bisa menenangkan. Namun, bagi Arga, suara itu hanya menjadi latar yang samar, seperti nada piano yang dimainkan dari kejauhan. Menyenangkan, tetapi tak cukup untuk menyentuh inti hatinya yang penuh keruwetan.
Selama beberapa menit, ia merasa berhasil. Tubuhnya mulai rileks, pikirannya sejenak tenang, dan bayangan masa lalu yang menghantuinya mereda. Di sela-sela hening itu, ia merasa ada harapan kecil. Mungkin alam memang punya caranya sendiri untuk menyembuhkan luka-luka yang manusia bawa tanpa sadar.
Namun, seperti awan senja yang cepat memudar, kedamaian itu pun tak bertahan lama.
Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan gradasi oranye keunguan di atas cakrawala. Arga membuka matanya dan menatap laut lepas yang kini berubah menjadi bayangan gelap misterius. Ia duduk di atas pasir, tangan menopang dagunya. Dinginnya angin malam mulai menusuk kulit, tetapi bukan itu yang membuat tubuhnya menggigil.
“Lari ke pantai ternyata tidak membuatku lebih baik.” gumamnya sambil menendang pasir di depannya.
Ia tahu sejak awal bahwa kabur ke tempat terpencil ini bukan solusi yang nyata. Ini hanyalah jeda. Seperti seseorang yang mencoba menekan tombol pause pada film yang tidak ingin ia tonton tetapi juga tidak bisa ia tinggalkan. Detik-detik tetap berjalan, dan akhirnya ia harus menekan play lagi.
Pikirannya berkelana ke berbagai momen yang telah ia coba lupakan. Pertengkaran terakhir dengan ayahnya, kepergian Kania tanpa pesan pamit, dan rasa bersalah yang tak kunjung hilang sejak malam itu. Semuanya kembali, seperti film buruk yang diputar berulang kali di kepala. Hampa menyeruak ke seluruh tubuh, membuat nafasnya terasa berat.
Arga berdiri dan mengibaskan pasir dari celananya.
“Cukup,” katanya tegas, meski tidak ada siapa pun yang mendengarkan.
“Kalau ketenangan tidak bisa menyelamatkanku, mungkin kekacauan bisa.”
Tanpa pikir panjang, ia berjalan kembali ke pondok kecil tempatnya menginap. Sebuah gubuk sederhana dengan atap rumbia yang ia sewa dari nelayan lokal. Di sana, hanya ada satu koper, sebotol air mineral setengah kosong, dan ponsel yang sejak tadi ia abaikan. Arga mengambil ponsel itu dan menatap layar yang mulai bercahaya.
“Sinyal lemah,” ujarnya sambil mendengus kecil. Ia melangkah keluar pondok, menuju satu titik di dekat pohon kelapa yang biasanya menangkap sinyal lebih baik. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil membuka aplikasi pesan.
Ia menggulir percakapan lama dengan beberapa teman di kota. Beberapa pesan belum dibalas, beberapa lainnya terlalu basi untuk dilanjutkan. Namun, ada satu nama yang membuatnya berhenti menggulir: Dani.
Dani adalah tipe teman yang tidak peduli jam berapa pun Arga menghubungi, ia selalu siap. Bukan karena ia peduli, melainkan karena Dani sendiri juga sering mencari pelarian di malam-malam sepi. Mereka berdua seperti dua kutub yang saling tarik menarik ketika malam tiba.
Arga mengetik pesan singkat: “Lu di mana?”
Balasan datang dalam hitungan detik: “Tempat biasa. Ayo ke sini.”
Tanpa berpikir panjang, Arga menutup ponselnya dan bergegas keluar pondok. Ia tidak peduli bahwa malam semakin pekat, bahwa angin semakin dingin, atau bahwa pantai ini terlalu jauh dari kota. Ia hanya tahu bahwa ia butuh sesuatu yang lebih membakar, lebih memicu adrenalin, dan lebih membuatnya lupa akan hampa yang terus menggerogoti.
perjalanan ke kota tidak secepat yang ia bayangkan. Jalanan berliku dan minim pencahayaan membuatnya harus ekstra hati-hati. Tapi ketika lampu-lampu kota mulai terlihat dari kejauhan, jantungnya berdegup lebih cepat. Seperti ada harapan baru di ujung jalan ini, meskipun ia tahu harapan itu rapuh dan sementara.
Arga akhirnya tiba di sebuah bar kecil di pinggir kota. Tempat biasa yang disebut Dani. Tempat ini bukan bar mewah dengan lampu kristal atau sofa kulit mahal. Sebaliknya, dindingnya terbuat dari kayu tua yang mulai lapuk, dan musik yang mengalun berasal dari jukebox yang suaranya sesekali ngadat. Namun, justru suasana inilah yang membuat tempat itu terasa nyaman bagi mereka yang ingin kabur dari kenyataan.
Dani duduk di sudut ruangan, ditemani segelas bir dan sebatang rokok yang asapnya melayang-layang seperti kabut tipis di bawah lampu kuning remang.
“Gue tahu lo bakal datang,” kata Dani sambil menyodorkan gelas bir kedua yang sudah dipesannya sejak awal.
Arga duduk dan meneguk bir itu tanpa banyak bicara. Rasanya pahit, tapi setidaknya lebih bisa ditoleransi daripada rasa pahit di hatinya.
“Apa yang lo cari malam ini?” tanya Dani, matanya memperhatikan Arga seolah mencoba membaca pikiran temannya.
Arga mengangkat bahu. “Gue nggak tahu. Mungkin cuma pengen lupa.”
Dani tertawa kecil.
“Lupa apa? Hidup kita memang layak dilupakan, Ga. Jangan terlalu dipikirin. Kalau gue, tiap malam begini, ya biar besok pagi gue nggak ingat apa-apa.”
Obrolan mereka mengalir seperti arus sungai yang tenang di awal, lalu mulai deras seiring malam semakin larut. Gelas demi gelas bir habis, dan suara tawa mereka bercampur dengan musik dari jukebox. Di sudut ruangan itu, untuk sementara, Arga merasa ia bisa melupakan beban yang menumpuk di dadanya. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu bahwa semua ini hanya ilusi.
Setelah beberapa saat, Dani menepuk pundak Arga.
“Ayo kita cari tempat lain. Gue tahu satu tempat yang bisa bikin lo lupa sama semuanya.”
Arga, yang sudah cukup mabuk untuk tidak peduli, hanya mengangguk. Mereka keluar dari bar dan naik ke motor milik Dani. Jalanan malam yang dingin tidak terlalu terasa, karena kepalanya sudah dipenuhi efek alkohol.
Tempat berikutnya adalah klub malam kecil yang terletak di gang sempit. Lampu-lampu neon berkedip-kedip, dan suara musik berdentum dari dalam. Begitu masuk, mereka disambut oleh aroma keringat, parfum, dan alkohol yang menyengat.
Arga berjalan melewati kerumunan orang yang menari, tangannya menggenggam botol minuman yang entah sejak kapan ada di tangannya. Semakin ia tenggelam dalam keramaian, semakin ia merasa terlepas dari kenyataan. Namun, di balik semua itu, ada suara kecil di dalam kepalanya yang terus berbisik.
“Ini tidak akan bertahan lama.”
Dan, benar saja. Setelah beberapa jam yang terasa seperti mimpi buram, Arga menemukan dirinya duduk di luar klub, punggungnya bersandar pada dinding yang dingin. Dani duduk di sampingnya, tertawa kecil sambil merokok.
“Gue nggak tahu apa yang lo cari, Ga. Tapi kalau pelarian, tempat ini nggak akan cukup,” kata Dani sambil menatap langit malam yang mulai memudar.
Arga menutup matanya, membiarkan dinginnya udara pagi menusuk kulitnya. Ia tahu Dani benar. Pelarian ini hanya akan membawanya kembali ke tempat yang sama—tempat di mana ia harus menghadapi kenyataan.
“Gue cuma… capek,” gumam Arga pelan.
Dani menghela napas panjang.
“Kita semua capek. Tapi lo harus nemuin alasan buat tetap jalan. Gue nggak bisa kasih tahu apa itu, tapi gue yakin lo bakal nemuin.”
Arga tidak menjawab. Ia hanya duduk di sana, membiarkan pagi datang perlahan. Hampa itu masih ada, tetapi kali ini, ia tidak mencoba melawannya. Mungkin, seperti laut yang pasang surut, perasaan itu akan hilang dengan sendirinya ketika waktunya tepat.
Mungkin.
Langit malam terasa berat, seperti selimut tebal yang membungkus kota dengan rahasia-rahasia yang tidak ingin diungkapkan. Lampu-lampu neon menari di sepanjang jalan, membentuk kilatan-kilatan warna yang tampak memabukkan. Jalanan kota besar ini tidak pernah tidur. Namun, bagi Arga, malam itu bukan sekadar pelarian; itu adalah pertempuran melawan dirinya sendiri.
Langkah kakinya terasa berat ketika ia melangkah masuk ke dalam klub malam yang penuh sesak. Dentuman musik elektronik menghantam gendang telinganya, menggema di dalam dadanya seperti genderang perang. Bukan perang melawan orang lain, tetapi perang dengan pikirannya sendiri. Dia melirik ke sekeliling—seorang pria dengan kemeja putih lusuh, rambut acak-acakan, dan sorot mata kosong yang jelas-jelas terlihat tidak menyatu dengan keriuhan di sekitarnya.
Pelayan bar yang berwajah ceria dengan senyum profesional mendekat, menawarkan daftar minuman. Arga tidak membutuhkan daftar. “Whiskey,” katanya pendek. Pelayan mengangguk dan berbalik. Beberapa menit kemudian, segelas cairan emas menghantam meja di depannya. Tanpa pikir panjang, Arga menenggak seteguk besar. Sensasi hangat membakar kerongkongannya, tetapi rasa sakit itu kecil dibandingkan kekacauan di dalam dirinya.
Di ujung ruangan, sekelompok orang tertawa terbahak-bahak, entah karena lelucon yang terlalu bodoh atau mungkin karena efek minuman yang sudah mengaburkan batas logika mereka. Seorang wanita dengan gaun merah berdiri di dekat DJ booth, menari dengan gerakan yang begitu bebas seakan dunia hanya miliknya. Arga menontonnya sesaat sebelum matanya kembali jatuh ke dalam gelas. Dunia ini terlalu penuh kebisingan untuk pikirannya yang penuh sesak.
Setiap tegukan whiskey terasa seperti usaha menghapus kenangan yang terus menghantui. Kenangan tentang keputusan-keputusan yang tidak bisa ia perbaiki, kesalahan-kesalahan yang tidak bisa ia hapus, dan kehilangan yang terus memburunya seperti bayangan kelam. Gelas pertamanya habis terlalu cepat, diikuti gelas kedua, ketiga, dan entah berapa lagi setelah itu.
Ketika mabuk mulai mengaburkan realitas, segala sesuatu di sekitarnya menjadi distorsi. Cahaya lampu neon tampak lebih cerah, suara-suara tawa terdengar lebih keras, dan waktu terasa melambat. Kepalanya mulai berat, tetapi pikirannya justru semakin liar. Rasa penyesalan, amarah, dan kesedihan bercampur menjadi satu, seperti badai yang tidak bisa dihentikan.
Seseorang menabraknya dari belakang, membuat gelas di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Arga berbalik dengan wajah kesal, tetapi pandangannya kabur.
“Apa masalahmu?” teriaknya kepada pria yang tampak tidak peduli.
“Tenang, bro,” sahut pria itu sambil tertawa, tetapi Arga tidak menemukan humor dalam situasi ini.
Pertengkaran kecil pun terjadi. Kata-kata kasar melayang di udara, dan tangan Arga sempat mendorong dada pria itu sebelum akhirnya seorang petugas keamanan klub datang melerai. Dia dibawa keluar, diusir seperti pengunjung tidak diinginkan yang membuat onar. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang menggigit.
Dia berdiri di trotoar, mencoba mencari keseimbangan di antara perutnya yang mual dan kepalanya yang berputar. Seolah-olah kota ini sedang menertawakannya, lampu-lampu jalan berkilauan seperti bintang yang menari. Jalanan lengang, tetapi pikirannya tidak. Ia berjalan tanpa tujuan, membiarkan langkah kakinya membawa dirinya entah ke mana.
Langit malam tidak berubah, tetap gelap dan diam, seolah mengamati manusia-manusia yang tersesat dalam jalur mereka masing-masing. Arga tidak tahu berapa lama dia berjalan sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah hotel kecil yang terlihat lusuh. Tanpa pikir panjang, ia masuk dan memesan kamar.
Kunci kamar berderak pelan ketika ia memutarnya. Kamar itu kecil dan sederhana, hanya ada tempat tidur, meja kecil, dan jendela yang menghadap ke jalanan kota. Lampu kuning redup menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding. Arga menutup pintu, menjatuhkan diri di atas tempat tidur, dan menatap langit-langit seolah mencari jawaban yang tidak pernah datang.
“Bahkan hura-hura pun tidak mampu membunuh kekosongan ini,” gumamnya, suaranya hampir tenggelam dalam kesunyian malam.
Matanya perlahan-lahan terpejam, tetapi pikirannya tetap berlari kencang. Ia terjebak di antara kenangan masa lalu dan kekosongan masa kini. Bayangan seseorang—wajah yang dulu pernah membuatnya merasa utuh—kembali hadir. Namun, bukannya memberikan kenyamanan, kenangan itu justru menambah luka.
Di dalam kesadarannya yang mulai memudar, Arga mendengar suara-suara samar. Entah itu suara mobil di jalanan luar, atau mungkin hanya imajinasinya sendiri yang mempermainkannya. Hatinya terasa hampa, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang dan tidak akan pernah bisa ditemukan kembali.
“Kenapa aku selalu kembali ke sini?” tanyanya dalam hati.
Tempat gelap ini, tempat di mana dia terus mencari pelarian tetapi tidak pernah menemukan jawaban. Jam berdetak pelan, mengiringi malam yang semakin dalam. Arga terjebak di antara kantuk dan kesadaran, di antara keinginan untuk melupakan dan rasa sakit yang tidak bisa ia hindari. Alkohol memang mampu membuat tubuh lelah, tetapi tidak cukup kuat untuk membungkam suara-suara di kepalanya.
Dalam keheningan itu, air mata mengalir tanpa izin. Bukan tangisan yang keras, tetapi lebih seperti air mata yang mengalir diam-diam, menandakan betapa dalam luka yang ia simpan. Ia mencoba menghapusnya dengan punggung tangan, tetapi air mata itu terus mengalir, seolah-olah tubuhnya tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan beban.
Beberapa saat kemudian, ia terduduk di atas tempat tidur, menatap bayangannya sendiri di cermin yang tergantung di dinding. Sosok itu terlihat seperti pria yang lelah, kehilangan semangat, dan tersesat dalam perjalanan hidupnya.
“Apa yang sebenarnya aku cari?” pikirnya.
Pertanyaan itu terus menggaung di dalam kepalanya hingga fajar mulai menyingsing, menandakan akhir dari malam panjang yang penuh kegelisahan. Matahari pagi perlahan-lahan menyelinap masuk melalui celah gorden, memberikan sedikit cahaya ke dalam kamar yang suram.
Dengan nafas berat, Arga bangkit dari tempat tidur. Kepalanya masih berdenyut karena efek alkohol, tetapi ia tahu ia harus bergerak. Ia berjalan menuju kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin, berharap itu cukup untuk menyadarkannya dari kekacauan batinnya.
Namun, saat ia menatap wajahnya di cermin kamar mandi, rasa kosong itu masih ada. Wajah itu mungkin segar setelah dicuci, tetapi matanya tidak bisa berbohong. Sorot mata itu masih penuh dengan rasa kehilangan dan penyesalan.
Arga menghela napas panjang. Ia mengenakan pakaian yang sama dengan malam sebelumnya, mengambil jaketnya, lalu keluar dari kamar hotel. Udara pagi terasa lebih segar, tetapi tidak cukup untuk menghapus beban di pundaknya. Langkah kakinya perlahan-lahan membawa dirinya kembali ke jalanan kota yang mulai ramai.
Orang-orang berlalu-lalang, terburu-buru dengan urusan mereka masing-masing. Arga merasa seperti penonton di tengah keramaian ini, seolah ia tidak benar-benar ada. Ia berdiri di tepi jalan, menatap langit biru yang mulai cerah.
“Mungkin aku butuh lebih dari sekadar pelarian,” gumamnya pelan.
“Mungkin yang aku cari bukan di sini.”
Langkah kakinya kembali bergerak, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di ujung jalan, tetapi ia tahu satu hal—ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi di balik malam dan alkohol. Sudah saatnya ia menghadapi rasa sakit itu, menghadapinya dengan kepala tegak. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan menemukan jawaban yang selama ini ia cari.
Langit sore mulai memerah ketika Arga menjejakkan langkahnya ke jalur pendakian pertama. Ranselnya berat, seberat pikirannya yang terus mengawang di antara masa lalu dan masa kini. Dalam kesunyian hutan yang lembab, ia seolah mendengar bisikan pepohonan yang mengingatkannya pada kenangan lama—tentang kegagalan, tentang mimpi yang belum tercapai, dan tentang seseorang yang dulu memberinya alasan untuk bertahan.
“Masih sempat mundur kalau mau,” suara itu datang dari belakangnya. Bayu, sahabat lamanya yang selalu menjadi penyeimbang di hidup Arga, tertawa kecil sambil menepuk pundaknya.
Arga hanya tersenyum tipis. Mundur bukan pilihan, pikirnya. Dia tahu dia harus terus maju, bukan karena ingin melarikan diri, tapi karena ingin menemukan jawaban yang entah tersembunyi di mana. Dia berharap, mungkin di balik puncak gunung ini, dia akan bertemu dengan ketenangan yang ia cari.
Sepanjang perjalanan, langkahnya terasa berat, tidak hanya karena jalan yang menanjak tetapi juga karena beban emosional yang menggumpal di dadanya. Namun, ada keindahan sederhana yang mulai meredakan ketegangan—suara burung, gemerisik daun, dan cahaya matahari yang menyelinap di antara dahan-dahan pohon. Alam seakan berbicara kepadanya dalam bahasa yang tidak ia pahami, tetapi cukup menenangkan.
“Lihat ke atas, Ga,” kata Bayu, menunjuk ke langit yang mulai berubah warna.
“Tiap pendakian itu kayak hidup. Kadang terjal, kadang ada bagian yang bikin kita pengin nyerah. Tapi di atas sana, ada pemandangan yang bakal bikin semua capek ini worth it.”
Arga mengangguk pelan. Mungkin Bayu benar. Atau mungkin dia hanya ingin percaya bahwa semua ini akan berujung pada sesuatu yang lebih baik.
Malam itu, mereka berhenti di pos perhentian pertama. Tenda mereka berdiri kokoh di antara rimbunnya hutan, sementara suara jangkrik mengisi malam. Arga duduk di depan api unggun, menggenggam secangkir teh hangat yang Bayu berikan. Namun, hangatnya teh tidak mampu mengusir dingin yang meresap ke dalam hatinya.
“Kenapa, Ga? Masih mikirin masa lalu?” tanya Bayu, tanpa basa-basi.
Arga tidak langsung menjawab. Matanya menatap kosong ke api yang menari-nari di depan mereka.
“Aku nggak tahu, Yu. Kadang rasanya semua yang kulakukan nggak ada artinya. Kayak aku cuma berputar-putar di tempat yang sama.”
Bayu tertawa kecil. “Semua orang pernah ngerasa kayak gitu, Ga. Tapi kalau kamu terus berhenti di situ, kapan kamu bakal sampai? Kadang kita cuma perlu tersesat dulu biar bisa nemuin jalan yang benar.”
Malam semakin larut, kabut turun perlahan, menyelimuti hutan dengan keheningan yang hampir mistis. Arga masuk ke tendanya, mencoba tidur meski pikirannya masih berkelana. Ia memejamkan mata, berharap esok pagi akan membawa jawaban.
Namun, pagi datang dengan ujian baru. Jalur pendakian semakin terjal, dan kabut tebal menyelimuti setiap sudut. Mereka tersesat.
“Tenang, kita nggak sendiri. Pasti ada jalan keluarnya,” kata Bayu, mencoba menenangkan Arga dan teman-teman pendaki lainnya.
Arga merasa panik, tetapi ia menutupi kegelisahannya. Di tengah kebingungan, mereka bertemu sekelompok pendaki lain yang ternyata tahu jalur alternatif. Berkat bantuan mereka, Arga dan timnya berhasil kembali ke jalur yang benar.
Saat mereka akhirnya menemukan jalan, Arga merenungkan kejadian itu. Mungkin seperti itulah hidup, pikirnya. Kadang kita harus tersesat dulu untuk menemukan arah baru. Bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa mampu kita bertahan di tengah kesulitan.
Mereka tiba di pos perhentian kedua menjelang sore. Angin dingin menyambut mereka, tetapi pos ini terasa lebih hidup. Ada sekelompok pendaki lain yang sudah lebih dulu sampai dan sedang berkumpul di sekitar api unggun.
“Gabung aja, Mas,” ajak seorang pendaki perempuan yang memperkenalkan dirinya sebagai Sinta. Dia tersenyum ramah, membuat suasana sedikit mencair.
Malam itu, mereka berbagi cerita. Ada cerita tentang keberhasilan, kegagalan, cinta yang kandas, dan mimpi-mimpi yang masih tertunda. Arga mendengarkan dengan saksama, merasa seperti menemukan potongan-potongan dirinya di dalam cerita orang lain.
“Aku dulu pengen banget jadi penyanyi,” kata Sinta sambil menatap api unggun.
“Tapi orang tuaku nggak setuju. Mereka bilang, aku buang-buang waktu. Aku sempat menyerah, tapi akhirnya aku mulai lagi dari nol. Aku nyanyi di kafe kecil sampai akhirnya aku bisa rekaman.” Wajahnya menunjukkan kehangatan meski suara lirihnya menyimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh.
Raka, seorang pria berusia tiga puluhan, menambahkan ceritanya.
“Aku dulu hampir menikah. Tapi calon istriku pergi sama orang lain. Aku nyaris nggak bisa bangkit. Sampai akhirnya aku sadar, aku nggak bisa terus-terusan hidup di bayangan masa lalu.” Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil.
“Pendakian ini, buatku, adalah cara membuktikan kalau aku masih bisa kuat.”
Kata-kata mereka menusuk ke dalam hati Arga. Ia sadar, semua orang punya beban. Setiap orang punya masa lalu yang ingin mereka taklukkan, dan disinilah mereka, berusaha mendaki gunung dalam upaya mendaki hidup mereka sendiri.
Keesokan paginya, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Jalur semakin terjal, tetapi semangat mereka semakin membara. Langkah demi langkah, Arga merasakan adrenalin bercampur dengan kelegaan kecil. Setiap langkah seperti simbol dari perjuangannya melawan dirinya sendiri.
Saat kabut mulai menipis, pemandangan hijau terbentang luas di depan mata. Gunung-gunung lain berdiri megah, seolah menyambut mereka yang telah berjuang keras untuk sampai di sini.
Ketika Arga akhirnya menginjakkan kaki di puncak, ia berdiri mematung. Matanya memandang luas, tetapi pikirannya berkecamuk. Perasaan lega, bahagia, dan ragu bercampur menjadi satu. Ia menangis, bukan karena lelah, tetapi karena merasa beban hidupnya sedikit terangkat—meski ia tahu, ini bukan akhir dari perjalanan emosionalnya.
Bayu menepuk punggungnya pelan.
“Lepasin aja, Ga. Kadang kita perlu nangis buat bener-bener bisa maju.”
Arga tersenyum di tengah tangisnya. Namun, jauh di dalam hatinya, keraguan masih bercokol. Ia bertanya-tanya, apakah puncak ini benar-benar membawa perubahan, atau hanya memberikan kelegaan sementara.
Malam itu, di dalam tenda yang dingin dan sunyi, ia kembali terjebak dalam pikirannya sendiri. Kesunyian mengungkap semua luka yang belum sepenuhnya sembuh. Sekalipun di puncak tertinggi, ia masih merasakan jurang batin yang dalam.
“Aku udah sampai puncak, tapi kenapa aku masih ngerasa kosong?” bisiknya pada dirinya sendiri.
Bayu, yang tidur di sebelahnya, ternyata masih terjaga.
“Mungkin karena kamu masih nyari jawaban di luar diri kamu, Ga. Padahal, jawaban itu ada di sini,” ucapnya sambil menepuk dada Arga.
Arga tidak langsung menjawab. Ia menutup matanya, berusaha mencerna apa yang dikatakan Bayu. Malam itu ia tidak mendapat kepastian, hanya serpihan kesadaran bahwa mungkin jawabannya masih menunggu di perjalanan berikutnya.
Dan Arga tahu, ia belum selesai. Masih banyak langkah yang harus ia tempuh, dan puncak ini hanyalah awal dari pencariannya yang lebih besar.
Langit pagi itu begitu cerah, seolah memberi restu untuk petualangan panjang yang direncanakan Arga sejak lama. Touring motor sendirian di jalan pegunungan adalah mimpinya sejak SMA. Kebebasan tanpa batas, angin yang menerpa wajah, dan suara mesin motor yang menjadi teman perjalanannya selalu menjadi fantasi yang tak kunjung hilang dari benaknya. Kini, ia akhirnya berada di sana, meniti aspal berliku, meninggalkan hiruk pikuk kota yang menyesakkan dada.
Arga menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara pegunungan yang segar memenuhi paru-parunya. Pemandangan di sekelilingnya begitu memukau: hamparan pohon pinus yang berdiri kokoh, tebing-tebing yang menjulang tinggi, dan kabut tipis yang menggantung di kejauhan. Sesekali, ia melirik ke spion dan tersenyum kecil. Tidak ada siapa pun di belakangnya. Tidak ada yang bisa mengganggu atau menghentikannya kali ini.
Saat motor meluncur di atas jalan berkelok, Arga merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada ruang kosong dalam dirinya yang perlahan-lahan terisi. Ia tak lagi memikirkan beban pekerjaan yang menumpuk atau hubungannya yang baru saja berakhir. Semuanya hilang, ditelan desir angin dan deru mesin. Hanya ada dia dan jalannya.
Setiap belokan jalan terasa seperti tarian. Gas dan rem menjadi ritme yang mengalun harmonis. Kakinya yang menekan pedal rem, tangan yang menggenggam erat setang motor, dan matanya yang jeli menatap jalan di depannya menciptakan keselarasan yang jarang ia rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, di atas motor dan di tengah alam liar, Arga merasa hidup sepenuhnya.
Namun kebebasan memang selalu punya harga. Dan jalan berliku itu, yang semula terasa seperti pelukan hangat, perlahan berubah menjadi tantangan berbahaya. Di sebuah tikungan tajam yang menurun, roda belakang motornya tiba-tiba kehilangan traksi. Arga mencoba menguasai kemudi, tapi terlalu terlambat. Motor tergelincir, dan dalam hitungan detik, tubuhnya terlempar ke pinggir jalan.
Ia jatuh di atas rerumputan yang lembab, tapi benturan keras di lutut dan pergelangan tangan membuat tubuhnya terasa seperti dihantam palu godam. Sesaat, semuanya terasa hening. Hanya suara angin dan desis mesin motor yang masih berputar pelan di kejauhan. Arga berusaha bangun, tapi nyeri yang menjalar dari lutut hingga ke paha membuatnya terkapar kembali. Ia meraih jaketnya yang robek di bagian siku, mencoba menahan rasa sakit dengan menggigit bibir bawah.
“Sial!” gumamnya, setengah berteriak, sembari memeriksa pergelangan tangannya yang membengkak.
Tangannya bergetar, dan ia tahu ada sesuatu yang salah. Mungkin retak atau bahkan patah.
Matahari yang tadinya bersinar cerah mulai meredup, digantikan oleh awan kelabu yang menggantung di langit. Malam datang lebih cepat di pegunungan, dan Arga mulai merasakan dinginnya angin malam yang menyusup ke sela-sela jaketnya yang sobek. Ia meraba saku celananya, mencari ponsel yang bisa menjadi penyelamat di saat seperti ini. Namun, tak ada sinyal. Layar ponselnya menunjukkan bar kosong, seolah-olah ikut mempermainkannya.
“Tidak mungkin…” Arga menggeleng pelan, mencoba menghapus rasa panik yang perlahan merayap ke seluruh tubuhnya. Ia melihat ke sekitar, berharap ada kendaraan lain yang lewat. Tapi jalan itu terlalu sepi. Tak ada suara mesin atau cahaya lampu dari kejauhan. Hanya kegelapan yang semakin pekat.
Satu jam berlalu. Rasa sakit di lututnya semakin menjadi-jadi. Darah yang tadinya hanya menetes pelan kini mulai mengalir deras, membasahi celananya. Arga menggigit kain jaketnya, mencoba menahan nyeri yang menusuk. Sesekali, ia memejamkan mata, berharap rasa sakit itu akan hilang begitu saja. Tapi kenyataannya, rasa sakit itu tetap ada, mengingatkannya bahwa ia sedang dalam masalah besar.
Di tengah rasa frustrasi, pikirannya melayang ke berbagai kenangan. Ia teringat percakapan terakhirnya dengan Dira, mantan kekasih yang meninggalkannya tanpa banyak penjelasan. “Aku butuh ruang,” kata Dira saat itu. Dan kini, ironisnya, Arga benar-benar mendapatkan ruang yang ia pikir ia inginkan—ruang kosong di pegunungan yang sunyi, tanpa siapa pun.
“Kenapa aku bisa sampai di sini?” bisiknya pelan, lebih kepada dirinya sendiri.
Ketika ia hampir menyerah, suara samar terdengar dari kejauhan. Suara azan subuh. Arga menoleh, matanya mencari-cari sumber suara itu. Ia melihat bayangan samar sebuah masjid kecil di kaki bukit, lampunya menyala redup. Suara azan itu terasa seperti panggilan dari tempat yang jauh, namun entah bagaimana mampu menembus dinding ketakutannya.
Air mata yang tadinya ia tahan perlahan mengalir. Arga menangis. Bukan karena rasa sakit fisik yang ia rasakan, tapi karena sesuatu yang lain—sesuatu yang lebih dalam, lebih personal. Tangisannya semakin menjadi-jadi, hingga ia tak lagi peduli pada luka atau pergelangan tangannya yang mungkin patah. Semua emosi yang selama ini ia simpan rapat-rapat tiba-tiba meledak seperti air bah.
Ia menangis untuk cinta yang gagal. Ia menangis untuk mimpi-mimpi yang hancur. Ia menangis untuk kesalahan-kesalahan yang ia buat, dan untuk semua hal yang tak bisa ia perbaiki. Di tengah jalan pegunungan yang sepi itu, Arga merasa seperti manusia paling kecil dan paling tak berdaya di dunia.
“Ya Tuhan,” bisiknya pelan di antara isak tangis. “Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan.”
Suara azan terus menggema, membimbingnya untuk tetap mendengarkan. Arga menutup matanya, mencoba merasakan setiap kata yang dilantunkan. Di sana, di tengah dinginnya malam dan rasa sakit yang mendera, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti ada kehangatan kecil yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak tahu pasti apa itu, tapi kehadirannya cukup untuk membuatnya merasa sedikit lebih tenang.
Setelah beberapa saat, tangisannya mereda. Ia menghela napas panjang, lalu mencoba duduk meski rasa sakit di lututnya masih terasa tajam. Perlahan, ia menggeser tubuhnya ke pinggir jalan, berharap posisi itu bisa memberinya sedikit kenyamanan. Di kepalanya, berbagai pikiran berkecamuk. Ia teringat pada masa kecilnya, saat ibunya selalu membisikkan doa di telinganya setiap kali ia merasa takut.
“Tuhan selalu ada, Arga. Bahkan di saat kamu merasa sendirian,” suara ibunya bergema dalam pikirannya. Kalimat sederhana itu, yang dulu sering ia abaikan, kini terasa seperti penopang terakhir yang ia butuhkan.
Matahari mulai muncul di ufuk timur, mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Warna oranye dan merah muda menghiasi langit, menciptakan pemandangan yang luar biasa indah. Arga tersenyum kecil, meski wajahnya masih basah oleh air mata. Ia merasa sedikit lebih kuat, meski rasa sakit di tubuhnya belum sepenuhnya hilang.
Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat cahaya lampu kendaraan mendekat. Sebuah mobil pick-up tua berhenti di depannya, dan seorang pria paruh baya keluar dengan wajah penuh kekhawatiran.
“Anak muda, kamu baik-baik saja?” tanya pria itu sambil membantu Arga berdiri.
“Saya… saya butuh bantuan,” jawab Arga lemah, suaranya bergetar.
Pria itu membimbingnya masuk ke dalam mobil, lalu menyalakan mesin. Selama perjalanan ke puskesmas terdekat, Arga memejamkan mata, membiarkan tubuhnya beristirahat. Di antara rasa sakit dan kelelahan, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mungkin bukan perubahan besar, tapi cukup untuk memberinya harapan.
Dalam perjalanan itu, ia mendengar suara lembut pria paruh baya yang berkata, “Kamu beruntung saya lewat di sini. Biasanya jalan ini sangat sepi di malam hari.” Arga hanya mengangguk lemah, tapi hatinya berterima kasih lebih dari apa pun.
Setibanya di puskesmas, perawat langsung sigap menangani lukanya. Arga berbaring di tempat tidur darurat, matanya menatap langit-langit putih dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, luka fisiknya akan sembuh. Pergelangan tangan yang patah bisa diperbaiki. Tapi ada sesuatu yang lebih penting yang perlu ia benahi—dirinya sendiri.
Pagi itu, saat ia terbaring di ranjang puskesmas, Arga membuat janji pada dirinya sendiri. Ia akan pulang. Ia akan menemui ibunya, memeluknya erat, dan mengatakan betapa ia merindukannya. Ia akan meminta maaf pada orang-orang yang pernah ia sakiti. Dan yang paling penting, ia akan memaafkan dirinya sendiri.
Perjalanan ini belum berakhir. Hanya saja, kali ini ia tahu ke mana ia harus pergi.
Matahari yang semakin tinggi di langit menghangatkan tubuhnya, seolah memberi isyarat bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Dengan hati yang lebih ringan, Arga tersenyum kecil. Mungkin kejatuhan ini adalah cara semesta mengajarinya sesuatu.
“Terima kasih,” bisiknya pelan, entah kepada siapa, mungkin kepada dirinya sendiri, kepada pria yang menolongnya, atau kepada suara azan yang membawanya kembali ke kenyataan. Tapi ia tahu satu hal pasti: ia akan terus berjalan.
Di luar jendela puskesmas, suara kehidupan pagi mulai terdengar. Burung-burung berkicau, suara orang-orang berbincang, dan langkah kaki yang sibuk. Arga menutup mata, menikmati momen itu. Perjalanan pulangnya baru saja dimulai, dan kali ini, ia siap menghadapi apa pun yang menantinya.
Arga duduk di tepi mushola kecil itu, punggungnya bersandar pada dinding kayu yang mulai lapuk oleh waktu. Cahaya temaram dari lampu gantung menyinari wajahnya yang lesu, bayangan lembut dari kerlip lilin di sudut ruangan menari-nari di dinding. Hujan yang sejak tadi turun mulai mereda, menyisakan gemericik air yang mengalir pelan di atap seng. Aroma tanah basah berpadu dengan wangi kopi dan singkong goreng dari meja kecil di dekat jendela.
Seorang bapak-bapak tua duduk bersila di seberangnya. Rambutnya sebagian besar telah memutih, tetapi matanya masih tajam, penuh kehangatan seperti seseorang yang siap mendengarkan tanpa menghakimi. Bapak itu menyesap kopi hitamnya perlahan, lalu menatap Arga yang masih terdiam.
“Kamu terlihat seperti orang yang tersesat,” katanya lembut.
Arga tidak menjawab. Matanya kosong, mengarah ke luar jendela yang menghadap ke pekarangan kecil mushola. Ia ingat jalan berliku yang ia tempuh, semua pelarian yang tak berujung dari satu kota ke kota lain, dari satu petualangan ke petualangan lain. Ia pikir, kebebasan ada di sana. Tapi sekarang, ia duduk di sini, di mushola yang sederhana, merasa seolah dirinya telah terperangkap dalam ruang hampa.
“Dulu saya pikir, pergi jauh itu jawabannya,” gumam Arga, suaranya pelan seperti hembusan angin malam. “Meninggalkan semuanya. Beban pekerjaan, harapan orang tua, kehidupan yang menyesakkan. Saya ingin bebas.”
Bapak itu tersenyum kecil, lalu mengambil sepotong singkong goreng dan meletakkannya di tangan Arga. “Kadang, kita memang perlu berlari untuk sadar bahwa yang kita cari tidak sejauh itu. Beban yang kamu bawa ke mana-mana mungkin bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri.”
Arga menggigit singkong itu, rasanya manis dan empuk. Tetapi ia tidak benar-benar merasakannya. Dalam hatinya, masih ada luka-luka yang belum sembuh.
“Apa bapak pernah merasa hilang arah?” tanya Arga.
Bapak itu mengangguk. “Tentu saja. Siapa yang tidak pernah? Waktu muda, saya juga pernah merasa dunia ini begitu besar dan saya begitu kecil. Pernah juga berpikir kalau hidup itu hanya berisi tuntutan yang tidak ada habisnya. Tapi, setiap perjalanan punya titik balik. Yang penting, kita tidak berhenti mencari. Karena Allah selalu dekat. Cuma kita yang kadang lupa jalan pulangnya.”
Arga menunduk. Kata-kata bapak itu sederhana, tapi menohok. Di antara suara angin malam, ia merasa seperti ditampar oleh kebenaran yang selama ini ia hindari.
“Ada satu ayat yang sering saya ingat kalau hati sedang berat,” lanjut bapak itu, menyesap kopinya lagi. “Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman, ‘Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), sesungguhnya Aku dekat.’ (QS. Al-Baqarah: 186). Kadang kita pikir Allah jauh, padahal Dia selalu menunggu kita kembali. Kita saja yang terlalu sibuk berlari dari rasa sakit, dari kenyataan, sampai lupa menoleh ke belakang dan melihat ada yang setia menanti kita.”
Arga memejamkan mata. Ia ingat malam-malam di apartemennya yang sunyi di Jakarta. Ia pernah duduk di sana berjam-jam, memandangi langit-langit tanpa tujuan. Ia mengira kebebasan adalah melupakan semua kewajiban. Tapi ternyata, semakin ia jauh dari shalat, dari doa, semakin hatinya kosong. Seperti mengejar bayangan di tengah padang pasir.
“Lalu bagaimana cara kembali?” tanyanya dengan suara serak. “Saya sudah terlalu jauh.”
“Tidak ada istilah terlalu jauh,” jawab bapak itu sambil tersenyum hangat. “Kamu tahu, Arga, Rasulullah pernah bilang bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Kalau kita melangkah satu langkah ke arah-Nya, Dia akan datang kepada kita dengan langkah yang lebih besar. Kembali itu sederhana: berhenti sejenak, akui bahwa kamu butuh pertolongan-Nya, dan mulai dari hal kecil. Seperti malam ini. Kamu duduk di sini, itu sudah langkah pertama.”
Arga merasa ada yang hangat di dadanya, seperti lapisan es yang perlahan mencair. Ia menatap tangan kosongnya yang dulu pernah mengepal marah karena dunia tak sesuai harapan. Kini, tangan itu terasa ringan.
“Dulu, shalat itu terasa seperti beban,” katanya jujur. “Saya tidak merasa butuh. Tapi sekarang, saya rindu. Entah kenapa, saya ingin shalat.”
Bapak itu tersenyum lembut. “Rindu itu tanda baik, Arga. Rindu kepada Allah adalah pertanda hati kamu mulai hidup kembali. Cobalah malam ini. Tidak perlu sempurna. Cukup ikhlas.”
Malam itu, Arga bangkit dari duduknya dan menuju tempat wudhu di samping mushola. Air dingin menyentuh kulitnya, membuat tubuh dan pikirannya terasa segar. Ia berdiri di atas sajadah kecil yang diberikan bapak tadi. Tak ada yang mewah, hanya selembar kain lusuh. Tapi, saat keningnya menyentuh sajadah itu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa seolah dunia yang berat selama ini terangkat dari pundaknya.
Ia mengucap takbir dengan suara pelan, namun hatinya gemuruh. Setiap gerakan terasa seperti pengakuan dan pelepasan. Ia ruku’, sujud, lalu duduk di antara dua sujud dengan air mata yang menetes tanpa bisa ia tahan. Di sanalah ia akhirnya mengerti, bahwa kebebasan bukan tentang melarikan diri, melainkan tentang melepaskan diri dari beban yang kita ciptakan sendiri.
Setelah selesai shalat, ia duduk kembali di tempatnya semula. Bapak itu masih di sana, menyesap kopi dengan santai seolah tidak ada apa-apa yang terjadi.
“Rasanya… aneh,” kata Arga, setengah tersenyum. “Tapi damai.”
“Damai itu yang kamu cari, kan?” jawab bapak itu, sambil memberikan segelas kopi kepada Arga. “Kadang, kita lupa bahwa damai bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita lepaskan. Kalau hati kamu penuh oleh amarah, kecewa, atau ambisi yang berlebihan, bagaimana bisa damai masuk?”
Arga memegang cangkir kopinya, merenungi kata-kata itu. Ia pernah mencoba mengisi kekosongannya dengan pekerjaan, uang, dan perjalanan ke tempat-tempat baru. Tapi, semua itu hanya seperti obat sementara.
“Bapak tidak pernah marah kepada Tuhan?” tanyanya penasaran.
Bapak itu terkekeh kecil. “Pernah, dulu. Waktu istri saya sakit dan tidak kunjung sembuh. Saya merasa Allah tidak adil. Tapi setelah saya lihat kembali, justru di masa sulit itulah saya benar-benar mengenal Allah. Saat saya merasa tidak punya siapa-siapa, ternyata Dia yang setia ada di sana.”
“Apa itu artinya semua penderitaan ada hikmahnya?”
“Bukan hanya hikmah, Arga. Penderitaan adalah cara Allah membersihkan hati kita. Kadang-kadang kita harus mengalami kegagalan besar supaya sadar betapa lemahnya kita. Tapi setelah itu, Allah bukakan jalan. Seperti malam ini. Kamu pikir kecelakaan yang membawa kamu ke sini itu kebetulan? Tidak, itu bagian dari rencana. Allah tahu kamu butuh jeda untuk berhenti dan mendengarkan-Nya lagi.”
Arga menyesap kopinya dalam-dalam. Pahitnya kopi itu seperti pengingat tentang semua rasa pahit yang pernah ia telan. Tapi kali ini, pahit itu terasa menenangkan. Tidak lagi menyesakkan.
“Terima kasih, Pak,” katanya lirih.
Bapak itu mengangguk pelan. “Terima kasihnya jangan ke saya. Saya cuma perantara. Terima kasihlah kepada Allah yang tidak pernah lelah menunggu kamu kembali.”
Hening sejenak. Suara jangkrik di luar terdengar nyaring, berpadu dengan gemericik air hujan yang masih menetes dari atap.
“Lalu, apa langkah selanjutnya?” tanya Arga.
“Kembali ke kehidupanmu,” jawab bapak itu. “Tapi kali ini, bawa serta Allah di setiap langkahmu. Jangan tinggalkan shalat lagi. Tidak perlu sempurna, cukup terus berusaha. Kalau kamu jatuh, bangun lagi. Karena Allah tidak pernah menyerah pada hamba-Nya.”
Arga menatap langit malam melalui jendela kecil mushola itu. Bintang-bintang yang tersembunyi di balik awan mulai muncul satu per satu, seolah ikut memberi harapan baru. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara malam yang segar memenuhi paru-parunya.
Beberapa minggu kemudian, Arga kembali ke kota yang sama, namun semuanya terasa berbeda. Jakarta yang dulu menyesakkan kini terasa seperti tempat baru, seolah-olah jalan-jalannya menyimpan harapan yang tak ia lihat sebelumnya.
Apartemennya masih sama. Jendela besar yang menghadap ke hiruk-pikuk jalan, meja kerjanya yang penuh kertas berserakan, bahkan secangkir kopi setengah kosong yang lupa ia buang sebelum pergi. Tetapi kali ini, apartemen itu tidak lagi terasa seperti sangkar. Tempat itu berubah menjadi ruang pulang, tempat ia menemukan dirinya.
Ia kembali bekerja, tetapi dengan semangat yang baru. Bukan untuk mengejar angka-angka atau jabatan, melainkan untuk memberi makna pada setiap hal kecil yang ia lakukan. Setiap sore, setelah pekerjaan selesai, ia melangkah ke masjid kecil di dekat kantornya. Ia duduk di sana, merenungkan perjalanan panjang yang telah membawanya pulang.
Suatu sore, di bawah langit yang mulai memerah, ia membuka jurnal pribadinya dan menulis:
“Aku kira jati diri harus dicari di tempat jauh. Ternyata, ia sudah ada di sini, menungguku membuka pintu hati.”
Tangannya berhenti sejenak, lalu ia melanjutkan:
“Allah tidak pernah jauh. Dialah yang dekat saat aku merasa sendirian. Dialah yang mendengar meski aku tak mengucap apa-apa. Setiap perjalanan, seberat apa pun, adalah cara-Nya menunjukkan bahwa aku hanya perlu kembali. Kembali kepada-Nya.”
Di halaman terakhir, ia menulis kutipan dari Al-Qur’an yang selama ini menjadi pengingat:
“Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? Dan Kami telah menghilangkan bebanmu darimu.” (QS. Al-Insyirah: 1-2)
Dengan senyum kecil di wajahnya, Arga menutup jurnal itu. Ia menatap keluar jendela, melihat kerlip lampu kota yang mulai menyala satu per satu. Malam ini, ia tidak lagi merasa gelisah. Ada damai yang meresap perlahan, memenuhi setiap ruang kosong yang dulu terasa menyesakkan.
Perjalanan ini telah selesai, tetapi langkah barunya baru saja dimulai. Seperti sungai yang akhirnya bertemu laut, ia tahu bahwa selama ia menjaga kompas dalam hatinya, ia tidak akan pernah tersesat lagi.
Di bawah langit malam Jakarta, Arga akhirnya pulang, dan kali ini, ia benar-benar pulang.
Kreator : wuntat widi
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak lahir begitu saja. Di balik perumusan lima sila yang menjadi pondasi bangsa ini, ada pemikiran mendalam dari para tokoh pendiri bangsa, salah satunya adalah Soekarno. Pemikiran Soekarno dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Lalu, apa saja pemikiran Soekarno tentang dasar negara […]
Dalam dunia pendidikan modern, pendekatan sosial emosional semakin banyak dibahas. Salah satu model yang mendapatkan perhatian khusus adalah **EMC2 sosial emosional**. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Definisi EMC2 sosial emosional? Mengapa pendekatan ini penting dalam pembelajaran? Mari kita bahas lebih lanjut untuk memahami bagaimana EMC2 berperan dalam perkembangan siswa secara keseluruhan. Definisi EMC2 Sosial […]
Part 15: Warung Kopi Klotok Sesampainya di tempat tujuan, Rama mencari tempat ternyaman untuk parkir. Bude langsung mengajak Rani dan Rama segera masuk ke warung Kopi Klotok. Rama sudah reservasi tempat terlebih dahulu karena tempat ini selalu banyak pengunjung dan saling berebut tempat yang ternyaman dan posisi view yang pas bagi pengunjung. Bude langsung memesan […]
Part 16 : Alun – Alun Kidul Keesokan paginya seperti biasa Bude sudah bangun dan melaksanakan ibadah sholat subuh. Begitupun dengan Rani yang juga melaksanakan sholat subuh. Rani langsung ke dapur setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Tidak lama disusul oleh Bude dan langsung mengambil bahan masakan serta mengiris bahan untuk memasak. Rani dan Bude sangat […]
Rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Soepomo memiliki peran sangat penting dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, Mr. Soepomo menjelaskan gagasan ini dengan jelas, menekankan pentingnya persatuan dan keadilan sosial. Dengan demikian, fokusnya pada teori negara integralistik membantu menyatukan pemerintah dan rakyat dalam satu kesatuan. Lebih lanjut, gagasan ini tidak hanya membentuk […]
Buy Pin Up Calendar E-book On-line At Low Prices In India After the installation is complete, you’ll have the flexibility […]
Karya Nurlaili Alumni KMO Alineaku Hampir 10 bulan, Pandemi Covid -19 telah melanda dunia dengan cepat dan secara tiba-tiba. Hal […]
Karya Lailatul Muniroh, S.Pd Alumni KMO Alineaku Rania akhirnya menikah juga kamu,,, begitu kata teman2nya menggoda, Yaa,,,Rania bukan anak.yang cantik […]
Karya Marsella. Mangangantung Alumni KMO Alineaku Banyak anak perempuan mengatakan bahwa sosok pria yang menjadi cinta pertama mereka adalah Ayah. […]
Karya Any Mewa Alumni KMO Alineaku Bukankah sepasang sejoli memutuskan bersatu dalam ikatan pernikahan demi menciptakan damai bersama? Tetapi bagaimana […]

Comment Closed: Kembali ke Jalan Pulang
Sorry, comment are closed for this post.